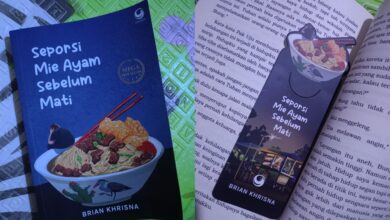HARAP DIAM
Aku berjumpa dengan tulisan itu di perpustakaan. Konon, siapa pun tidak boleh bicara terlalu keras atau sebaiknya tidak perlu bicara sama sekali di perpustakaan. Perpustakaan tampaknya hendak menciptakan suatu masyarakat yang tenang, tetapi isi kepalanya penuh dengan informasi.
Tulisan itu menggantung di langit-langit. Dicetak dengan huruf kapital seluruhnya. Berwarna hitam. Latar belakang tulisan itu atau warna papan plastik yang digunakan berwarna putih. Kontras. Sudah cukup untuk dapat dilihat dengan mudah.
Perintah serupa, sering kudengar ketika aku masih kecil.
Sebagaimana umumnya anak kecil yang normal, aku selalu bertanya apa ini dan apa itu. Orang-orang di sekitarku, tentu saja yang lebih tua dariku, menjawab semampu mereka. Selama pertanyaan itu tidak mustahil untuk dijawab, mereka akan menjawabnya sambil tersenyum.
Namun, ketika pertanyaan itu menyangkut hal-hal yang mengesalkan, seperti seseorang berjaket kulit hitam dengan sepatu pantofel mengilap yang datang ke rumah dan menerima uang dari orang tuaku, aku tidak pernah mendapat jawaban siapa orang itu. Ketika aku sudah besar, setelah masuk SD, baru aku tahu bahwa orang semacam itu disebut sebagai penarik kredit. Kredit apa pun.
Aku tumbuh seperti anak-anak normal lainnya. Aku mengetahui hal-hal baru sesuai dengan takaran normal. Pada intinya, aku adalah anak normal: setiap pagi, ketika berusia kanak-kanak, ibuku akan menyisir rambutku ke samping kiri dan tidak akan membiarkan satu pun rambut tegak. Menurutnya, begitulah gaya rambut anak rajin dan penurut. Anak yang penurut dan tidak banyak membantah adalah anak baik. Ya, aku telah tumbuh menjadi anak baik. Sampai besar pun dan ketika menjadi mahasiswa seperti saat ini, aku tidak pernah mengubah gaya rambutku. Aku sudah menjadi anak yang taat kepada ibunya karena tidak pernah mengubah gaya rambut yang dikehendaki seorang ibu kepada anaknya.
Aku berkuliah secara wajar: masuk kelas, menyimak perkuliahan dan membuat catatan, membaca lebih banyak buku dari teman-temanku, dan, ini yang paling penting, aku tidak berisik. Aku membuka mulutku hanya untuk makan dan minum dan menguap, juga ketika hendak menyampaikan jawaban yang ditanyakan, jawaban itu pun bersifat seperlunya.
Pada suatu ketika, di masa lalu, aku pernah mengatakan sesuatu yang mengerikan. Karena hal itu, aku perlahan-lahan dijauhi oleh teman-temanku. Aku tidak begitu mengerti di mana letak kesalahanku. Kuusahakan bertanya kepada mereka, tetapi mereka menjawab: lebih baik kau diam saja! Seperti anak manis, seperti biasanya! Aku turuti mereka. Sejak saat itu aku tidak begitu banyak bicara—meskipun kurasa gejala ini sudah ada sejak diriku masih kecil.
Konsekuensi menjadi anak pendiam adalah aku tidak begitu menyukai kebisingan. Aku tidak tahan ketika ada salah seorang pengunjung perpustakaan memukul-mukul pahanya sesuai irama musik yang didengarnya melalui earphone. Hal semacam itu benar-benar mengganggu konsentrasiku. Aku juga tidak suka keributan sehingga tidak menegurnya. Aku mengemasi buku-buku yang sedang kubaca dan pergi ke tempat yang lebih sepi. Itu lebih bijak menurutku.
Aku telah belajar cukup baik dengan peribahasa menang jadi arang, kalah jadi abu. Pertama kali aku mengetahui peribahasa itu adalah ketika mata pelajaran Bahasa Indonesia di SD, aku lupa kelas berapa tepatnya. Sejak saat itu aku meminta uang kepada ayahku untuk membeli sebuah buku kumpulan peribahasa. Dia memberiku dengan serta-merta karena aku anak baik.
Aku membeli buku kumpulan peribahasa itu di sebuah bazar buku di sekolah. Setelah membeli buku yang kuinginkan, aku bergegas menuju kelas, duduk di bangkuku, dan membalik halaman demi halaman dari buku itu. Diam itu emas. Itu adalah peribahasa yang memukau, berkilauan di kedua mataku. Aku menerapkan peribahasa itu sebaik mungkin. Aku bahkan tidak menghiraukan guruku ketika beliau memanggilku. Sepulang sekolah aku disuruh menghadap kepadanya. Aku turuti itu karena aku adalah anak baik. Aku duduk di sebuah ruang kosong, di sana guruku tadi sudah menungguku.
Dia bertanya kepadaku, “Mengapa tadi tidak menjawab? Bukankah kamu tahu jawabannya? Kamu adalah anak yang pandai.”
Aku tidak menjawab.
“Apa ada masalah? Ceritakanlah kepada ibu,” katanya sekali lagi.
Aku masih diam.
Guru itu akhirnya menyerah. Dia menyuruhku membawa orang tuaku besok ke sekolah untuk urusan ini. Setelah aku mengangguk sebagai tanda paham, aku diizinkan untuk pulang. Aku memberitahu ibuku dengan kalimat yang sangat jelas: ibu dipanggil sekolah. Ibuku terkejut. Hanya ada dua hal mengapa seorang wali murid disuruh datang ke sekolah: siswa ini bermasalah atau ada sebuah prestasi yang didapatkan anaknya.
Ibuku bertanya kepadaku, “Apa yang kamu perbuat, Nak?”
Aku menggeleng.
Ibuku mungkin menganggap itu sebagai ketidaktahuan. Dia pun sedikit tenang.
Keesokan harinya ibuku datang ke sekolah bersamaku.
Guru tadi mulai berbicara, “Anak ibu adalah anak yang pandai. Dia selalu mendapat ranking satu. Dia teladan kelas untuk urusan pelajaran. Tapi, akhir-akhir ini, dia selalu menutup mulutmya seolah enggan untuk berbicara. Apakah ada suatu hal yang terjadi di rumah?”
Ibu yang bersikap sangat tenang. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa tidak ada masalah di rumah sehingga memengaruhi kehidupan sekolahku.
Guru itu kembali bertanya, kali ini kepadaku, “Lalu mengapa kamu diam saja?”
Karena tidak ingin duduk berlama-lama di ruangan ini, aku mengambil sebuah buku di dalam tasku. Membuka halaman yang sudah kutandai dengan kertas dan menunjukkan kepada guru itu sebuah kalimat: Diam itu emas. Guru itu tertawa, tetapi tidak cukup keras dan segera menghentikannya. Dia kemudian mengatakan kepada ibuku bahwa ibuku bisa pulang.
“Kalau begitu,” kata ibuku, “saya titipkan anak saya di sekolah ini.”
Guru itu mengangguk dan mengiyakannya.
Mereka berdua berjalan ke luar ruangan dan bersalaman. Guru itu kemudian kembali lagi kepadaku dan memberitahuku bahwa aku seharusnya tidak menelan mentah-mentah setiap hal yang kutemui dalam buku itu.
Dia bertanya kepadaku, “Apa artinya peribahasa itu?”
Aku berpikir sejenak. “Orang yang berharga adalah orang yang banyak diam.”
Guruku tersenyum sekali lagi. Dia kemudian mulai menasihatiku, “Jawabanmu tidak salah. Memang jika kita banyak bicara, biasanya kita sedikit bekerja. Tapi bukan berarti kita tidak boleh bicara sama sekali. Bicara tentang hal-hal yang perlu dan bermanfaat saja, itulah yang diperbolehkan.”
Sejak saat itu, aku menuruti nasihatnya, seperti anak baik.
***
Menjadi anak baik seolah sudah ditakdirkan untukku. Anak baik adalah anak yang tidak begitu banyak bicara, selalu menuruti perkataan orang tua, guru, atau atasan. Menjadi anak baik adalah hal yang paling mudah untuk dilakukan di dunia ini. Aku tidak perlu repot-repot untuk menimbang-nimbang apakah tindakanku ini baik atau buruk. Tidak ada beban pikiran sama sekali ketika aku menjalani hidup, sekolah, kuliah, sampai bekerja. Aku menyukai kehidupan semacam ini. Aku hanya perlu menjalankan instruksi.
Dengan menjadi anak baik sepertiku, segalanya bisa sangat lancar. Sekarang aku diterima di sebuah perusahaan dan bekerja dari pukul tujuh sampai pukul empat sore. Karena aku menjadi anak baik, aku juga tidak terlambat menikah. Orang tuaku sudah menyiapkan calon yang pas untukku. Istriku juga adalah tipe anak baik. Dia selalu menuruti perkataanku. Kami hidup seperti kereta api yang selalu mengikuti relnya. Dengan demikian, kecelakaan tidak akan terjadi. Kami akan sampai tujuan dengan selamat.
***
Ketika anak pertamaku lahir, aku memberinya nama yang baik-baik. Selalu membisikinya perkataan yang baik-baik. Kujauhkan dia dari lingkungan yang buruk agar tidak terpengaruh. Aku cukup yakin bahwa lingkungan sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak-anak. Aku sendiri adalah contoh yang sempurna untuk hal tersebut. Aku selalu hidup di lingkungan yang baik-baik, berteman (meskipun dalam jumlah sedikit) dengan orang-orang baik, yang satu tipe denganku. Sebisa mungkin, aku menjauhi kehidupan kotor, buruk, dan bebas. Kebebasan adalah sesuatu yang berlebihan dalam hidup. Orang-orang bebas cenderung liar dan tidak taat aturan. Mereka tidak memiliki kepatuhan sedikit pun terhadap segala aturan yang berlaku di dunia ini.
Bukan hanya lingkungan luar yang baik, lingkungan di dalam rumah tanggaku pun harus selalu kupastikan menjadi lingkungan yang baik. Aku sama sekali tidak pernah cekcok dengan istriku. Sesama anak baik tidak mungkin bertengkar. Aku yakin akan hal ini, istriku juga demikian. Karena aku telah mencecap kebahagiaan sebagai anak baik, aku harap anakku juga mencecap hal yang serupa, kalau bisa bahkan lebih baik dariku.
Ketika dia sudah mulai berjalan dan berbicara, aku ajarkan kepadanya kepatuhan dan kata-kata baik. Seiring berjalannya waktu, dia sudah waktunya masuk sekolah. Aku memilih sekolah elite, yang baik dan memiliki kedisiplinan tinggi. Istriku mengantarnya dan menjemputnya. Semua biaya memang tidak murah, tetapi aku sudah memiliki gambaran bahwa hal ini akan berhasil. Aku lebih giat lagi bekerja, bahkan beberapa kali mengambil lembur, agar kebutuhan sekolah anakku terjamin.
Anakku tidak pernah protes. Dia selalu mengikuti arahanku, arahan ibunya, dan arahan guru-gurunya di sekolah. Memang, dia tidak tampak tersenyum selama menjalani semua itu. Tapi yang terpenting adalah dia tidak protes, tidak mengeluh, dan tidak memberontak. Buah memang tidak jatuh jauh dari pohonnya.
Ketika masuk SMP, hal serupa juga kulakukan. Aku mencari sekolah yang lebih disiplin lagi. Sepengetahuanku, anakku menjadi anak yang sangat disiplin, juga tidak banyak bicara. Dia tidak pernah telat bangun. Dia bahkan memiliki jadwal kegiatannya. Itu baik. Dengan demikian, dia akan tumbuh menjadi anak yang super baik. Kelak, dia pasti memiliki karier yang cemerlang. Aku berani bertaruh.
SMP tempat anakku bersekolah lebih disiplin lagi. Tidak ada toleransi keterlambatan dan berbagai pelanggaran tata tertib yang berlaku. Seragam harus dimasukkan, memakai dasi, dan rambutnya harus dipotong pendek. Ketika aku berkunjung ke sana untuk melakukan survei (aku mengambil cutiku yang tidak pernah kuambil untuk hal ini), kudapati anak-anak di sana berwajah serius dan tenang. Wajah mereka hampir mirip satu sama lain, sulit untuk membedakannya. Tidak ada yang banyak omong membicarakan hal-hal yang tidak berfaedah. Hanya diskusi-diskusi tentang pelajaran. Luar biasa!
Kupikir, saat itu juga, sekolah ini adalah tempat yang cocok. Aku bertanya kepada para guru di sana. Mereka juga menjujung tinggi tata tertib. Tidak ada celah di tempat itu. Aku pulang dan memberitahu istriku bahwa anak kami harus bersekolah di sekolah itu, bukan di tempat lain. Aku menunjukkan brosur sekolahnya kepadanya. Dia langsung menyetujuinya. Aku bertanya kepada anakku, dia langsung setuju. Aku tahu. Ini adalah cara mendidik paling minim risiko.
Sekolah dimulai. Anakku tidak perlu lagi diantar istriku karena dia sudah cukup besar untuk mengendarai sepeda sendiri. Aku membelikan perlengkapan bersepeda secara komplet: pelindung kepala, siku, dan lutut, serta sarung tangan dan kacamata. Dia mengenakannya dengan bangga dan berangkat sekolah dengan riang.
Di hari Sabtu dan Minggu, sekolah libur. Anakku hanya diam di rumah sambil membaca buku-buku pelajarannya di dalam kamarnya. Beberapa hari terakhir dia bahkan mengurung diri di dalam sana. Sebelum mengunci pintu kamarnya dari dalam, dia berkata kepada kami bahwa dia ingin belajar dan tidak mau diganggu. Aku tidak masalah. Itu hal baik, super baik. Aku yakin dia akan maju dalam pendidikannya.
Hari Senin tiba, tapi anakku belum juga bangun. Kurasa, dia belajar terlalu larut kemarin malam sehingga terlambat bangun. Istriku mengetuk pintu kamarnya beberapa kali, tapi tidak ada jawaban sama sekali. Akhirnya, dia menggunakan kunci cadangan, tetap tidak berhasil karena pintunya digerendel dari dalam. Aku pun mendobraknya beberapa kali. Begitu pintu terbuka, istriku berteriak. Sebuah seprei dan selimut yang diikat menjadi satu menggantung pada kayu yang menyangga genting rumah. Di ujung paling bawah, kedua kaki anakku, satu-satunya anakku, tidak menyentuh lantai. Sepertinya, dia telah gagal menjadi anak yang baik. Sungguh disayangkan.
22 Oktober 2020—29 Juli 2022
Baca Juga: Bayangan Masa Depan