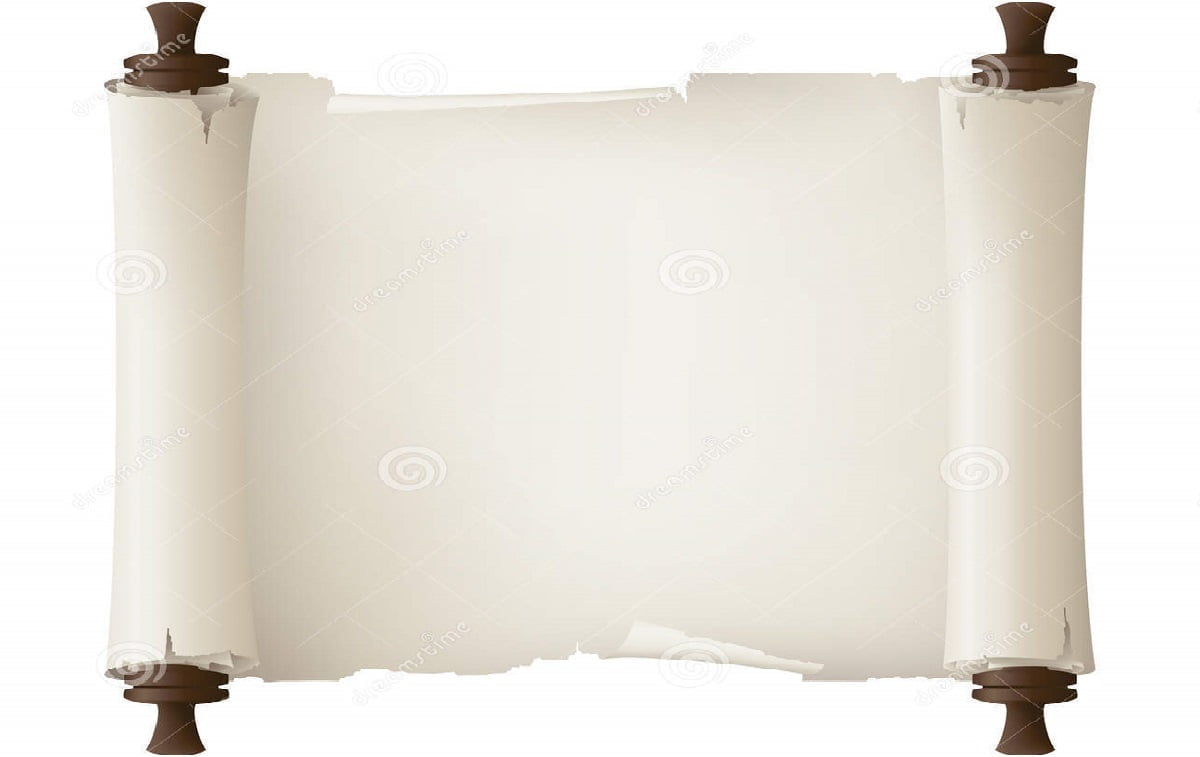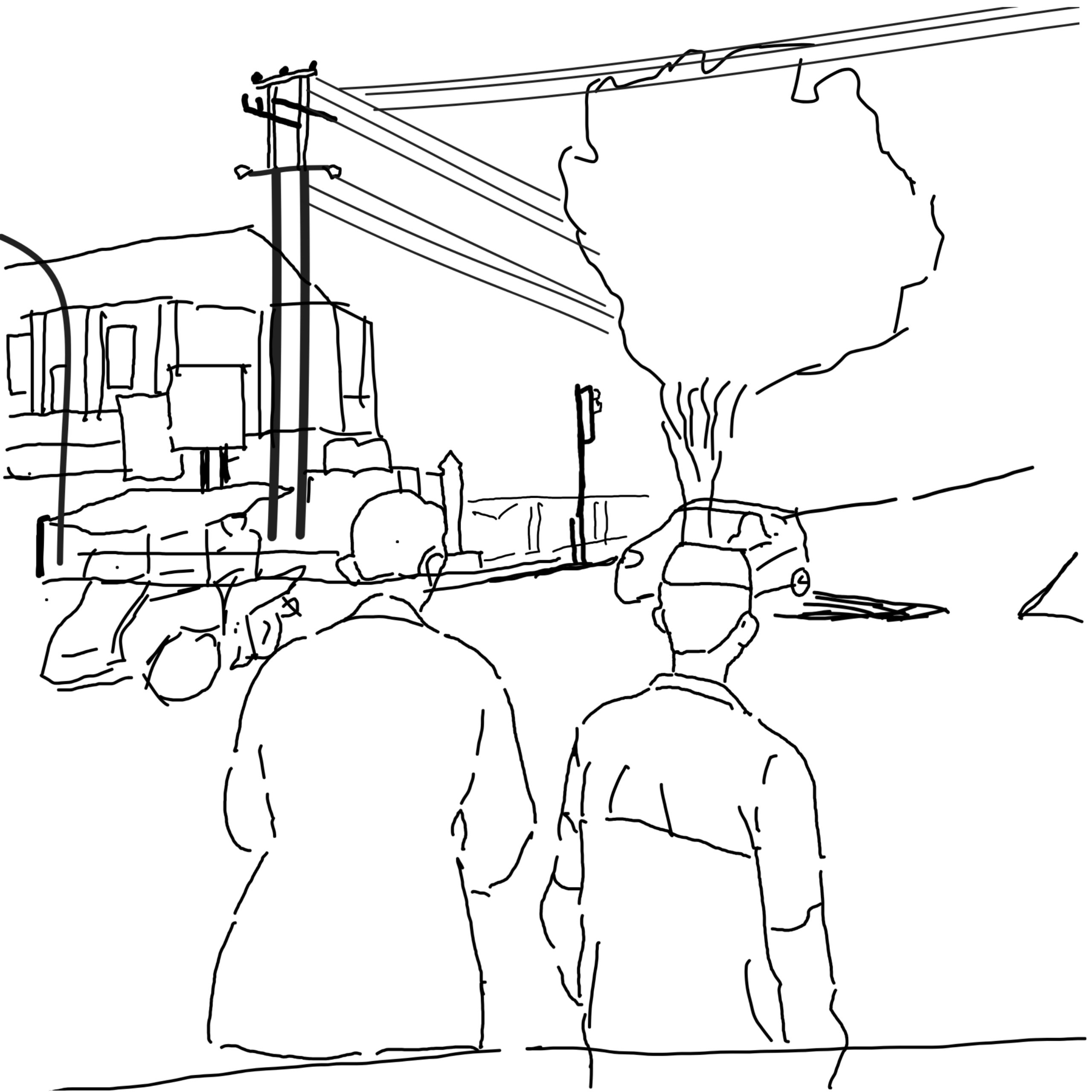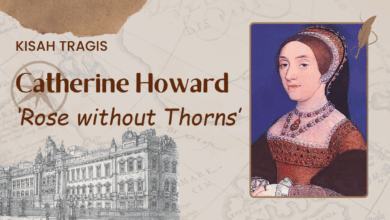Nama dan Kecemasan-Kecemasan
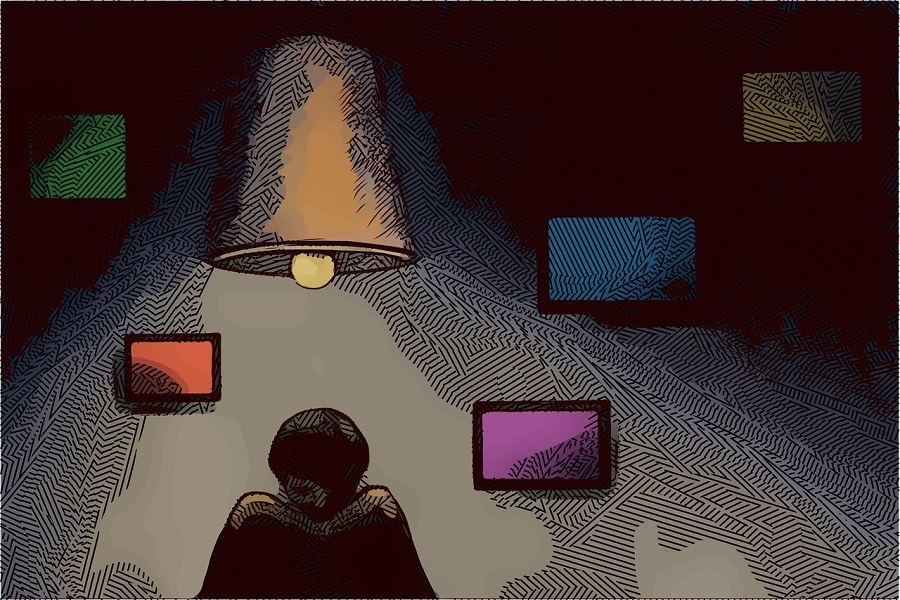
Namaku Ali Nursan. Sejak 1961, aku diasingkan dari rahim ibuku. Padahal, dengan kecemasan-kecemasan, aku keluar – lebih tepatnya dikeluarkan dengan paksa.
Padahal, di dalam rahim ibuku, aku lebih hebat. Lebih hebat dari segala. Tanpa harus mencari makan, sudah bisa melepas lapar. Tanpa harus mencari air, sudah lesap rasa hausku. Entah kemana.
Janin, nama lain dari seribu kebahagiaanku. Tapi bayi, adalah nama-nama terpenting bagi orang tua. Tapi apa pedulinya bapak. Ia pergi meninggalkan ibu di pulau yang penuh derita dan siksa, dan kecurigaan-kecurigaan. Tapi siapa yang tak saling curiga di sini? Ketika aku lahir dan diberi nama untuk kehidupan, semua mencurigai ibu. Bedebah!
Kenapa harus saling curiga jika semua bisa berjalan semestinya? Aku benar-benar tak paham. Bapak yang meninggalkan ibu, bahkan mungkin bukan hanya tak paham, tapi tak mau tahu tentang ibu yang sakitnya bertubi-tubi dicerca huru-hara.
Aku benar-benar tak suka dilahirkan. Tapi siapa yang bisa memilih mati dengan sendirinya semasa bayi? Tidak ada. Semua berkat ibu. Ibu yang merawatku dengan kecemasan-kecemasan. Dengan daun-daun waktu yang terus berjalan maju. Berlari dikejar angin ribut. Dan, waktu. Waktulah yang telah mengajariku bertahan dalam kecemasan-kecemasan.
***
Aku lihat di wajah ibu ada urat-urat cantik yang bahagia. Padahal aku tahu betul, ia tidak sedang bahagia. Ia sedang cemas. Diliputi kecemasan yang teramat menukik. Melilit. Bahkan, kecemasan itulah yang dicurigai telah mengambil nyawa orang-orang mati. Dan aku hidup setelah orang mati menanggalkan kehidupannya yang penuh kecemasan.
Ibu sering menimangku dengan muka yang selalu saja begitu: pura-pura bahagia. Ah, ibu, kenapa ibu suka sekali membohongi kebusukan hidup ini di hadapanku? Kenapa? Apa karena aku masih bayi dan tak tahu persoalan-persoalan kehidupan?
Ya, aku memang masih bayi. Masih tak tahu perihal-perihal. Tak tahu catatan-catatan kecemasan ibu, yang ibu simpan dalam-dalam dalam hatinya.
***
“Kelak, kamu akan dewasa, Ali Nursan. Kelak, kamu akan dewasa dan melepaskan kecemasan-kecemasan ibumu ini dari tubuhnya yang ringkih. Kelak, Ali Nursan. Suatu saat nanti. Pasti!” Setiap kali ibu menimangku, ia pasti menangis dan meminta agar aku menjadi dewasa. Dewasa?
Maaf ibu, aku tak bisa menjawab dengan sungguh. Apa ibu pernah menjadi kanak? Ah, ibu, aku hanyalah bibit-bibit kecemasan. Aku tak janji. Aku tak janji bisa melunasi utang-utang kecemasanmu pada dunia ini. Maaf ibu. Maaf.
***
Dan waktu. Waktu selalu meminta manusia untuk mengubah perasaan. Aku benar-benar merasa iba melihat ibu. Ibu, kelak, dalam waktu dekat, aku akan tumbuh dewasa. Kelak, ibu tak usah khawatir lagi perihal kecemasan-kecemasan. Aku akan mencabut kecemasan itu dalam tubuhmu. Aku janji. Aku janji, Ibu.
Tapi, perjanjian hanya tinggal perjanjian. Ibu tak mengerti. Tak paham bahasaku. Dan, bagaimana mungkin aku melepaskan kecemasan ibu jika melepasakan kecemasanku sendiri saja tak bisa. Aku benar-benar cemas untuk hidup lebih lama lagi di dunia ini. Aku tak sanggup melihat ibu dalam kesendirian dan dipenuhi kecurigaan-kecurigaan orang-orang. Mengapa manusia harus saling mencurigai? Aku tak paham. Benar-benar tak paham.
***
“Nak, bangun. Jangan tinggalkan ibu. Nak, bangun.” Aku mendengar suara ibu. Tapi sungguh, aku benar-benar tak bisa membuka mata. Tak bisa meng-eak seperti biasanya. Di mana aku ini? Apakah masih tetap di dunia yang penuh kecemasan itu? Syukurlah kalau aku sudah pergi meninggalkan kejahanaman itu.
Tidak. Tidak. Aku tidak boleh pergi. Aku tidak pergi. Aku sudah berjanji pada ibu. Aku sudah berjanji pada ibu untuk melepaskan sayap-sayap kecemasannya yang semakin hari semakin lebar.
“Baena, tabahkan hatimu, Nak. Dia sudah pergi ke rumahnya yang lain.” Aku dengar Nenek Tua itu menyebut nama ibu. Dan “dia”? Siapa “dia”? Aku? Tidak. Aku tidak boleh meninggalkan ibu yang selalu diserbu kecemasan itu. Tidak akan!
Ibu menangis sekuatnya. Aku mendengarnya. Mendengar suara itu. Suara ibu yang mengamuk pada semesta. Jangan ibu! Jangan! Aku tidak pergi.
***
Air mata memeta. Mengalir ke seluruh tubuhku yang mungil. Ibu mendekapku kuat-kuat. Aku tak tahan. Aku ingin beri tahu ibu bahwa aku tak pergi. Tapi aku sungguh-sungguh tak kuasa. Tak bisa berbuat apa-apa.
***
Suara itu. Aku mendengarnya lagi. Ya, suara Nenek Tua itu terlepas lagi dari mulutnya yang buas dan berbusa, “Jangan terlalu lama menangisinya, Baena. Semua yang datang, pasti akan pulang. Kamu jangan terlalu memaksa kehendak.”
Tidak! Anakku belum mati. Ali Nursan masih hidup. Ayo nak, bangun! Kamu tak boleh mati. Tak boleh meninggalkan ibu sendiri. Ayo nak, bangun!” Ibu mengguncang-guncang badanku ke kanan dan ke kiri. Mengguncang lagi. Mengguncang lagi. Mengguncang dan mengguncang. Lagi dan lagi dan lagi. Jangan, Ibu. Jangan. Aku tidak pergi, ibu. Tidak!
“Sudahlah, Baena. Jangan gila!”
***
Nenek tua itu. Tahu apa dia tentang kehidupan? Aku belum pergi. Dan tidak boleh pergi. Aku harus bisa. Aku harus bisa membuka mata ini. Meng-eak kuat-kuat. Harus. Harus bisa. Harus!
“Lihat, anakmu sudah tak berdaya. Dia sudah mati, Baena. Jangan siksa anakmu yang sudah mati. Dia tak bakal hidup tenang di alam sana.”
Sombong! Tahu apa Nenek Tua itu tentang kehidupan dan kematian? Aku belum mati. Aku masih di sini menemani ibu dalam kecemasannya. Tapi, sungguh, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Jasadku hanya diselimuti ruh yang terbang ke sana ke mari. Ruh! Kenapa kamu permainkan jasadku? Lihat ibuku, ia tak berhenti menangis dan dituduh gila. Ruh! Tolong. Tolong kasihani ibuku. Jangan tambah penderitaannya. Biarlah ibuku bahagia dengan kehadiranku di sisinya, walaupun hanya dengan kebahagiaan yang pura-pura. Setidaknya ia bisa terlihat bahagia.
***
Ternyata kecemasan tetaplah kecemasan. Setelah lama sekali ruhku hanya terbang melingkar di atas jasadku dan tak menghiraukan permintaanku, ruhku perlahan-perlahan masuk dalam jasadku untuk yang kedua kalinya. Tapi, tidak. Ia keluar lagi. Dan, ya, suara. Ruhku mengeluarkan suara, yang tentunya hanya bisa kudengar sendiri. Dan suara itu berbeda dari yang lain, tidak seperti suara, tapi aku mendengarnya. Keras sekali. Tapi, sungguh suara itu aneh dan tidak seperti suara. Tapi sangat keras. Lantang: kecemasan… kecemasan … kecemasan … dan begitulah berulang-berulang. Agaknya ruhku telah cemas.
Tapi siapa yang tidak cemas hidup di dunia yang begitu lemas ini? Siapa? Tolong aku, Ruh! Tolong aku. Aku mau membahagiakan ibu. Bukankah kecemasan ditakdirkan untuk membahagiakan, Ruh? Tolong, Ruh. Tolong aku.
Kecemasan … kecemasan … kecemasan …
***
Mungkin, lantaran kecemasanlah bapak pergi meninggalkan kami. Aku pahami itu setelah umurku telah mencapai 4 tahun hidup di dunia ini. Ya, di tahun 1965 ini, di mana semua orang terlalu mencemaskan kehidupan dan identitas, dan saling mencurigai secara berlebihan. Tapi, aku tetap tidak akan memaafkan bapak. Tidak mungkin memaafkan kesalahan yang lahir dari kecemasan dan kecurigaan yang tak berdasar. Apalagi di pulau ini, di pulau yang selalu diselimuti kecemasan dan ketakutan untuk mengenal orang lain.
Aku paham, kenapa kecemasan ibu padaku selalu meluap-luap bahkan melampau-lampau melebihi kecemasannya pada dirinya sendiri. Ibu selalu curiga pada kesehatanku yang selalu berubah-ubah. Sedikit-sedikit sakit. Dan, untuk semua itu, ruhkulah yang harus bertanggungjawab. Tapi, ruhku hanya membalasnya dengan suara yang bukan suara : kecemasan … berulang-ulang.
***
Hingga suatu ketika, satu hari setelah ibuku dilanda kecemasan besar, lantaran mautku hampir-hampir saja melesapkan ruhku jauh-jauh dari tubuhku, Nenek Tua itu memprovokasi ibu agar segera mengubah namaku.
“Tapi, namanya sudah ciamik. Kenapa harus diubah?”
“Ia tak akan sembuh. Ia akan dibunuh namanya.”
Bangsat! Tahu apa Nenek Tua itu soal nama-nama dan rasa sakit? Tapi, karena tak bisa apa-apa lagi, Ibu mengubah namaku: Toropak.
Dan setelah 6 tahun menyandang nama itu, kecemasan muncul lagi. Kali ini, kecemasan itu benar-benar besar. Semua keran kecemasan telah dibuka dari berbagai penjuru negeri oleh pemimpin negeri ini.
Dan setelah semua keran kecemasan itu sudah terbuka. Bangunan-bangunan semakin menjulang tinggi. Infrastruktur negeri semakin menggila. Semua kecemasan disulap menjadi kebahagiaan. Tapi, kecemasan tetaplah kecemasan. Orang-orang semakin cemas. Mereka berbondong-bondong untuk menutupnya.
Hingga 27 tahun semenjak keran itu dibuka, orang-orang berhasil menutupnya. Termasuk aku. Akulah orang yang hampir mati tertembak pelor tentara-tentara waktu itu. Tapi kami berhasil menutup keran kecemasan itu. Kami benar-benar berhasil.
Tapi, kecemasan tetaplah kecemasan. Ia terus tumbuh dan berkembang bersamaku. Bersama lima nama yang sering kuubah-ubah setiap bertemu dengan kelompok tertentu. Kadang Ali Nursan, Ibnu Hajar, Abdullah, Suki, dan Toropak.
Semua ini lantaran Nenek Tua itu. Bangsat!
Baca Juga: Sagara