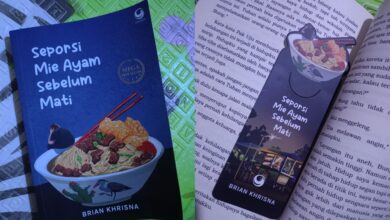Kasak-kusuk tetangga nyaring terdengar, berbisik nyinyir soal pelakor yang katanya mulai masuk kampung. Obyek pembicaraan yang dimaksud yakni anak gadisnya Ajengan Jujun. Namanya Neng Sintia. Jangankan ikut nimbrung dengan tetangga. Keluar rumah pun sangat jarang, kecuali untuk sekolah atau berangkat mengaji.
Usia Neng Sintia masih sangat belia, 19 tahun. Kulitnya pucat tapi bibirnya merah alami. Kemarin-kemarin ia masih jadi gadis pendiam dan cukup disegani karena berstatus anak kiai. Tapi rencana pernikahannya dengan seorang duda menuai banyak pergunjingan. Pasalnya, sang duda baru saja bercerai dengan istri tuanya, dan Neng Sintia dikabarkan menjadi dalang hancurnya rumah tangga mereka.
Entah siapa yang memulai, tapi cap “pelakor” seketika tersemat di jidat Neng Sintia. Sebutan ini mengandung konotasi yang hina, bahkan setiap perempuan sepertinya sangat alergi dengan sesamanya yang menyandang predikat ini.
Apa itu pelakor? Apakah ia semacam monster berbulu lebat, atau makhluk jadi-jadian yang bertaring dan bermata merah menyala?
Rupanya bukan.
Kuamati dari kejauhan, penampakan Neng Sintia masih seperti yang kemarin-kemarin. Ia masih cantik dan kalem. Bedanya, sejak isu pelakor beredar dan ditujukan untuk Neng Sintia, sinar matanya tampak meredup. Tak tampak lagi senyum manis di wajahnya. Padahal itu adalah salah satu bekal bahagiaku dalam menyambut hari.
Tidak banyak orang yang tahu, Neng Sintia adalah bagian dari rutinitasku yang terindah. Setiap jam 6 pagi, sepulang iktikaf di masjid, aku akan selalu lewat di depan rumahnya. Ini pada awalnya tak disengaja. Tapi jalan menuju rumah harus melewati rumah sang gadis pujaan hatiku itu.
Ketika sinar matahari masih malu-malu menunjukkan kehangatannya, aku selalu mendapati Neng Sintia menyapu halaman rumah. Ucapan “permisi” yang selalu kulontarkan di hadapannya, disambut dengan senyum manisnya, sembari membungkukan badan. Neng Sintia dan semua orang di kampung ini tak tahu, pertemuan yang hanya beberapa detik saja itu kuandalkan sebagai bekal semangat dalam menjalani hari-hari yang penuh tanda tanya.
Ah… Tapi itu masa lalu.
Kini, tak bisa lagi kunikmati senyumannya di pagi hari yang seperti vitamin yang menyehatkan hati.
***
Selidik punya selidik, Pelakor merupakan suatu istilah yang belakangan ini terdengar ramai di televisi, dipopulerkan oleh sejumlah tayangan infotainment, merujuk pada praktik perselingkuhan yang melibatkan kalangan artis. Pelakor adalah kepanjangan dari “perebut laki orang”, atau ada juga yang menyebutnya “perawat laki orang”. Intinya, orang yang disebut pelakor ialah para perempuan yang dianggap merebut laki-laki yang sudah punya istri.
Seperti diketahui, praktik poligami sangat tidak populer, bahkan cenderung dibenci oleh masyarakat modern, terutama kalangan perempuan, meski dalam agama dibolehkan. Masyarakat telah terbiasa dengan rumah tangga gaya monogami, di mana ada satu suami dan satu istri, lalu mereka membesarkan anak-anak yang lucu.
Maka kehadiran wanita idaman lain, atau wanita simpanan, atau apalah istilah yang beredar, adalah hal yang tercela, bahkan dalam banyak kasus menghasilkan konflik dan kehancuran rumah tangga. Praktik-praktik tersebut bisa melibatkan siapa saja, tak harus melulu selebriti.
***
“Heran, kenapa pinangannya diterima? Nikah siri pula,” kata Ceu Odah sambil bibirnya manyun.
“Itulah kalau pertimbangannya sudah ke harta, jadi gelap mata. Tahu sendiri dosen itu statusnya PNS,” Ceu Isah menimpali.
“Jagain tuh suaminya, ibu-ibu! Sekarang pelakor bukan di TV aja, tapi udah masuk kampung,” Ceu Mimin ikut nimbrung.
Obrolan mereka berlangsung dari hari ke hari, tak kenal waktu, tak kenal tempat. Jelang pernikahan Neng Sintia, cibiran-cibiran tetangga makin nyaring terdengar. Terlebih pernikahan mereka akan dilakukan secara tertutup, hanya disaksikan keluarga dan orang-orang terdekat saja. Tak satupun tetangga diundang.
***
Ajaibnya, Neng Sintia yang notabene adalah mantan kekasihku, mengundangku untuk menyaksikan pernikahannya. Sehari sebelum ijab qabul, ia mengirim pesan WhatsApp, memintaku dengan sangat agar bisa menghadiri pernikahannya.
Aku jadi teringat tentang bagaimana pada awalnya kami saling jatuh cinta, menjalin hubungan yang santun selama tiga tahun. Neng Sintia adalah teman sekelasku ketika di SMA dulu. Anaknya cantik, sopan dan tidak banyak bicara. Hal yang paling aku suka darinya adalah senyuman indah yang sanggup membuatku terpaku diliputi bahagia, saking manisnya.
Ia tak pernah keberatan dibonceng pakai motor butut. Ia juga selalu tersenyum meski aku hanya bisa membelikannya kerudung murahan untuk hadiah ulang tahunnya. Tapi kemudian hubungan itu harus berakhir karena Ayahnya tak suka denganku yang kala itu berstatus pengangguran. Siapa sudi punya mantu luntang-lantung tanpa penghasilan yang jelas?
Ketika hubungan cinta kami berakhir, ia mendadak jadi orang asing. Aku tak lagi bisa mengajaknya untuk sekadar ngobrol, atau berjalan-jalan keliling kampung. Aku tahu, itu bukan keinginannya. Buktinya, ia masih sudi tersenyum untukku, dengan sinar mata yang penuh harap. Benarkah ia ingin aku berjuang lebih keras agar bisa dianggap layak untuk menjadi suaminya? Atau aku yang terlalu gede rasa.
***
Entah bagaimana awalnya hingga kemudian Neng Sintia jadi bulan-bulanan warga dengan status pelakor. Mengapa istilahnya harus pelakor? Mengapa seolah-olah kesalahan atas kehancuran rumah tangga seseorang hanya ditujukan pada pihak wanita?
Bagaimana dengan si lelaki yang katanya Dosen itu? Mungkin pada awalnya dia yang mulai menggoda Neng Sintia. Mungkin juga sebenarnya Neng Sintia tidak menginginkan pernikahan itu. Ia hanya menuruti keinginan ayahnya yang selalu egois.
Memilih untuk berprasangka baik selalu lebih baik dari pada nyinyir dan mengotori mulut sendiri.
Mengapa harus dinamakan pelakor? Perebut laki orang. Adakah pada awalnya seorang suami memang milik istrinya. Logikanya apa hingga orang menganggap bahwa ada kepemilikan diantara dua orang yang menikah? Sebab menurutku, ketika dua orang menikah, mereka tetap punya independensinya masing-masing.
Sebelum atau sesudah menikah, mereka tetaplah orang yang punya kedaulatan dan pilihan sendiri. Mereka juga tentunya punya pilihan untuk tetap bersetia pada istri dan keluarganya, ataukah ingin menjalankan karma buruk dengan melakukan praktik perselingkuhan.
Kesesatan istilah pelakor juga tampak nyata, sebab praktik perselingkuhan itu melibatkan dua orang. Bukan hanya perempuan, tapi laki-laki juga harus dideteksi kesalahannya, jika mau. Tidak mungkin perempuan disebut “pelakor” kalau ia tidak kena rayuan, atau rayuannya disambut oleh suami orang.
Lantas aku bertanya-tanya lagi, di manakah logikanya istilah pelakor? Mengapa mulut para ibu-ibu itu terlalu jahat, padahal mereka sama-sama perempuan. Mereka juga mungkin punya anak atau saudara perempuan. Bukannya saling membela, mengapa memilih saling menjelek-jelekan.
Terlalu bising orang berteriak-teriak tentang pelakor. Padahal istilah itu sama sekali tidak ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berbahasa saja mereka masih seenaknya, bagaimana mungkin mereka berani-berani usil dan menjadi hakim atas hidup orang lain. Mereka bahkan tidak tahu dan tidak mau tahu kalau misalnya Neng Sintia membela diri dan memberikan klarifikasi suatu saat nanti.
***
Aku pun memutuskan untuk menghadiri pernikahannya. Dengan setelan batik dan celana panjang hitam yang sudah usang, aku duduk di bangku dekat pelaminan. Aku bisa memperhatikan dengan jelas kerutan-kerutan yang tegas di wajah pengantin pria, serta uban yang terselip ramai di rambutnya. Benarkah Neng Sintia akan benar-benar akan menerima pria tua bangka itu jadi suaminya?
Tak lama, penghulu datang dan pengantin wanita segera dipanggil agar segera bersanding dengan calon suami di pelaminan. Neng Sintia bak putri raja yang diborgol tangan dan kakinya. Wajahnya penuh dengan riasan mewah. Tapi bagiku, itu seperti topeng yang mengenaskan.
Kuperhatikan, pengantin pria mulai melafalkan ikrar ijab qabul. Tangan Ajengan Jujun digenggamnya dengan mantap. Ia sepertinya ingin segera menyelesaikan ritual suci itu dengan mulus.
“Bagaimana, saksi, sah?” penghulu bertanya.
“TIDAK SAH!”
Sebelum saksi yang ditunjuk mengangguk dan membuat persetujuan, aku lebih dulu berdiri, berteriak, dan segera menarik perhatian.
Seperti yang sudah kuduga, semua orang kaget, termasuk Neng Sintia. Tapi kalau aku tak salah lihat, ada segurat senyum di wajahnya. Senyum itu sama seperti yang selama ini kurindukan, dan sempat hilang ketika dia dicap pelakor oleh orang-orang sekampung.
Tapi aku tak bisa menikmati senyuman itu lama-lama. Beberapa pria bertubuh besar segera menyeretku keluar. Itu wajar, karena biang rusuh harus segera dilenyapkan, agar situasi kembali kondusif.
Rupanya upayaku berhasil. Segera setelah aku diusir keluar, Neng Sintia kabarnya menangis histeris, lalu secara tegas menolak untuk menikah. Bapak Penghulu memutuskan untuk pulang, dan meminta pihak keluarga menyelesaikan masalah internal dengan kepala dingin. Sudah seharusnya beliau berlaku begitu. Bukankah tidak boleh ada paksaan dalam pernikahan?
***
Hari-hari berlalu setelah pernikahan Neng Sintia berakhir huru-hara. Kasak-kusuk Neng Sintia Pelakor sudah reda. Sebagai gantinya, orang kampung punya obyek gosip pengganti yang tak kalah sedap dibahas. Adalah aku, yang kini mendapatkan predikat sebagai “Selingkuhan Pelakor”.
Ah, terserah apa kata logikamu saja, kawan.
Baca Juga: Di Batas Khayal
BekelSego adalah media yang menyediakan platform untuk menulis, semua karya tulis sepenuhnya tanggung jawab penulis.