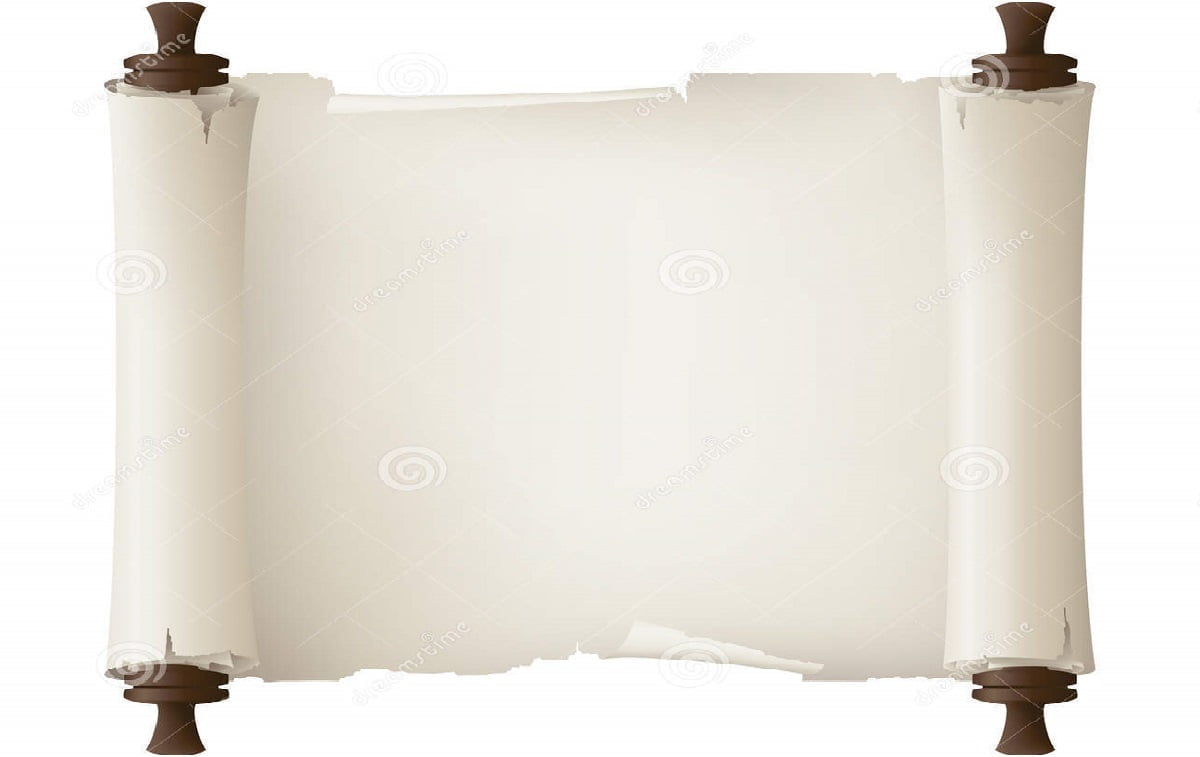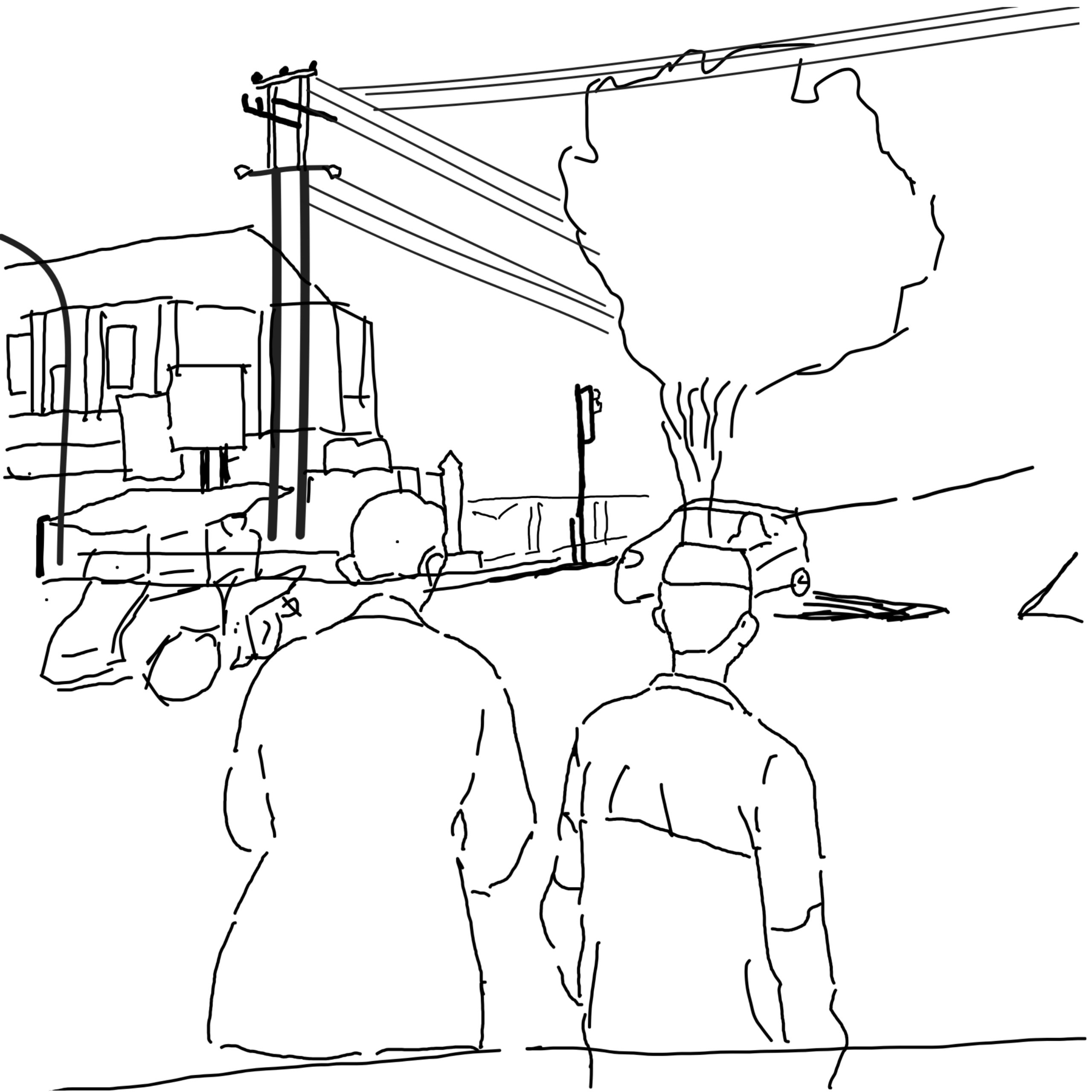Cara Kerja Ingatan
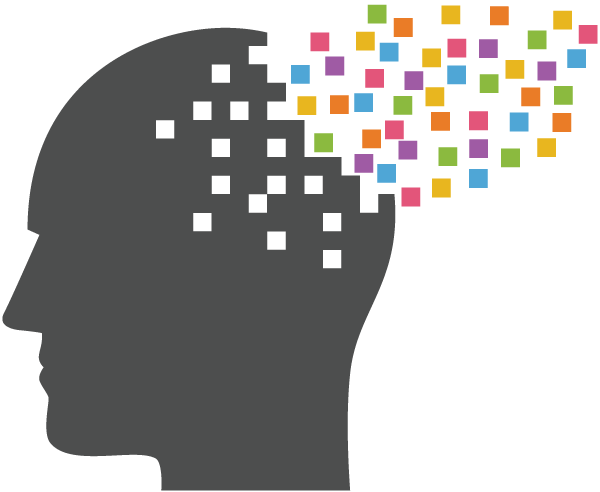
Awalnya saya kira, saya benar-benar akan dikeluarkan dari pondok. Gara-gara permainan futsal yang terlalu kasar, saya menonjok Abdul. Kaki kiri saya serasa mau patah waktu ia merebut bola dari giringan saya dengan cara yang tak wajar. Alhasil, saya geram dan tangan kiri saya membuat pipinya bengkak. Untung saja, Karim dan kawan-kawan lain segera melerai. Siang itu juga saya disidang Ustadz Damhuri di halaman pesantren dan disaksikan seluruh santri.
“Hanafi, kamu tahu apa yang telah kamu lakukan?” Lantang suara Ustadz Damhuri mengawali sidang itu. Tubuh saya bergetar. Kawan-kawan saya yang tadi ikut bermain tak ada yang membuka mulut. Keringat di tubuh saya mengucur bukan hanya lantaran ketakutan yang luar biasa, tapi terik matahari ikut menyengat tubuh saya.
Saya melirik Karim. Ia hanya menunduk. Saya tak bisa berkata-kata.
“Sekali lagi, Hanafi. Kamu tahu apa yang telah kamu lakukan?” Suara Ustadz Damhuri membuat sekujur tubuh saya kaku. Lutut saya seakan retak. Mau saya rubuh karena ketakutan yang luar biasa. Saya tak bisa berkata-kata. Saya melirik lagi ke arah Karim. Ia tetap menunduk.
Saya melirik ke sekeliling halaman. Astaga. Semua santri berkumpul dan memperhatikan saya. Sungguh malu saya. Saya tidak mampu angkat bicara. Keringat di tubuh saya mengucur semakin deras.
“Kalian, perhatikanlah apa yang saya ucapkan ini,” Ustadz Damhuri meninggikan nada suaranya, “Hanafi telah melakukan kesalahan yang sangat luar biasa. Memukul santri lain sangatlah tidak dibenarkan. Maka, untuk itu, Hanafi harus dihukum. Sesuai dengan peraturan pesantren, Hanafi harus dikeluarkan karena kesalahan tidak mampu menahan nafsunya dan melukai santri lain.”
Saya lemas mendengar kalimat Ustadz Damhuri. Tiba-tiba, saya sudah ada di sebuah ruangan. Bapak dan Ibu saya berada di samping saya.
“Untunglah, kamu sudah siuman. Sudah dua hari kamu terbaring, Nak.” Kata Ibu. Bibirnya membuat senyum simpul. “Lain kali, jangan macam-macam di pesantren.” Tambahnya sambil mengelus kepala saya yang rambutnya sudah hampir sebahu.
“Nak, ini baru kali pertama Bapak dan Ibu kemari karena ulahmu. Bapak tidak mau dengar lagi ada kekacauan di pesantren karena kesalahanmu.” Timpal Bapak.
Saya terkesiap. Mereka tahu dari mana saya telah membuat kesalahan? Agaknya, mereka dapat telepon dari pengurus pesantren kalau saya telah menonjok Abdul. Tapi, kenapa saya masih ada di ruang kesehatan pesantren? Bukankah kemarin saya telah divonis untuk dikeluarkan?
Belakangan, saya tahu, waktu Ustadz Damhuri menyatakan saya akan dikeluarkan, saya langsung pingsan. Dan saat saya pingsan, Karim angkat bicara. Ia menceritakan bagaimana kasarnya si Abdul menendang kaki kiri saya dan dengan reflek, saya langsung menghajar pipi Abdul.
Saya dibopong ke ruang kesehatan. Abdul menjadi pengganti saya di halaman pesantren. Ia disidang, lalu kemudian, ia mendapat hukuman “cukur botak” saat itu juga. Ah, untunglah si Karim berani angkat bicara. Saya harus berterimakasih padanya.
Bapak dan ibu saya pulang setelah saya sudah benar-benar boleh kembali ke kamar saya. Sebelum pulang, Bapak berpesan pada saya, “Nak, jangan sekali-kali nafsumu menguasai tubuhmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.”
Saya hanya tertunduk. Malu. Segera saya menuju kamar ketika derum mobil kijang Bapak terdengar semakin kecil. Saya harus cepat-cepat berterimakasih pada Karim. Sambil menahan sakit yang masih terasa di kaki kiri saya, saya langkahkan kaki. Dan… belum sempat lima langkah, Ustadz Damhuri menghampiri saya. Ia menyerahkan sepucuk surat. Dengan senyum ramah ia berkata, “Besok siap-siap,” Ustadz Damhuri menatap saya sambil memegang kedua bahu saya, “suratnya dibaca di kamar saja.” Lanjutnya dengan wajah tetap ramah dengan senyum yang tulus sambil mengelus-elus rambut panjang saya.
Setiba di kamar, saya langsung temui Abdul. Kepalanya botak dan pipi kanannya ada memar berwarna ungu tua di dekat mata sipitnya. Saya langsung minta maaf. Dia tersenyum simpul lalu memeluk saya erat-erat. “Saya juga minta maaf”, katanya, “Saya tidak bermaksud bermain kasar.” lanjutnya. “Tak apa,” jawab saya, “Karim di mana?” tanya saya kemudian. “Entahlah.”
Tak lama setelah saya dan Abdul bercengkerama dan saling maaf-memaafkan, Karim tergopoh-gopoh masuk ke kamar. Saya dan Abdul mengerutkan dahi, dan serentak kami pun bertanya, “Ada apa?”
Karim kemudian tertawa kecil, “Syukurlah kamu sudah siuman, Naf. Saya kira kamu bakalan sampai seminggu di ruang kesehatan.”
Saya dan Abdul saling pandang. Kami tidak paham maksud Karim. Alih-alih menanyakan apa yang telah membuatnya tergopoh-gopoh, saya dan Karim kemudian tertawa terbahak-bahak. Celana Karim penuh kotoran sapi.
Karim sadar, saya dan Abdul menertawakan dirinya yang dipenuhi kotoran sapi. Segera ia mengambil handuk dan pakaian ganti. Lalu melesat menuju kamar mandi. Ah, belum juga saya sempat berterimakasih padanya sudah main kabur saja, batin saya.
Setelah shalat subuh dan semua tempat sudah luput dari kata “kotor”, demikianlah, peraturan tetaplah peraturan. Harus selalu ditegakkan. Tanpa basa-basi dan penolakan, saya langsung menuju tengah lapangan. Para santri segera berkumpul mengililingi saya seperti waktu saya divonis akan dikeluarkan dari pesantren. Ustadz Damhuri sudah siap untuk menyampaikan dalil-dalilnya di depan para santri. Saya sudah tak gentar lagi. Saya akui kesalahan saya. Saya siap dicukur botak. Saya siap kehilangan rambut kesayangan saya. Saya ikhlas.
Usai rambut saya dicukur, saya dan Abdul menjadi begitu mirip. Semacam kembar tapi beda. Sama-sama memiliki kepala bak matahari yang merindukan bulan di tengah teriknya yang menyengat. Karena itulah, saya dan Abdul dijuluki macam-macam oleh teman-teman yang lain. Ada yang menjuluki “Onde-onde tanpa wijen”, “Gundu bersaudara”, “Globe”, dan banyak lagi ragamnya yang serupa tapi tak sama.
“Ustadz,” salah satu santri saya tiba-tiba unjuk jari, “kenapa celana Karim bisa penuh dengan kotoran sapi?” tanyanya.
“Karim lupa, Nak, kalau main bola itu tak boleh dekat-dekat kandang sapi.” Jawab saya sambil sedikit menyunggingkan senyum.
Sontak seluruh ruangan jadi riuh dengan gelegar tawa. Saya ikut tertawa seperti mereka. Masa lalu, begitu indah masa lalu. Saya ingat benar bagaimana muka Karim ketika saya tanya perihal kotoran sapi waktu saya bertandang ke rumahnya. Katanya, “Jangan ingatkan saya soal itu. Aib. Mohon dikunci rapat-rapat. Hehe.” Saya juga ingat bagaimana Abdul melarikan pembicaraan ketika saya ingatkan perihal kejadian di lapangan futsal pesantren.
Begitulah cara kerja ingatan, terkadang membuat kejadian-kejadian sedih masa lalu menjadi lucu di kemudian hari.
Hukuman yang menimpa saya menumbuhkan semangat baru. Kepala saya boleh tak ada rambut, tapi otak harus selalu diisi. Saya lebih giat belajar. Saya selalu ingat-ingat pesan dari bapak ketika saya didatangi rasa malas. Demikianlah sampai hari ini saya berada di sini, pesan-pesan itu tetap berkelabatan dalam ingatan saya.
Bapak pergi ke tempat lain yang abadi dua tahun sebelum saya lulus dari pesantren tidak membuat hati saya bergeming untuk patah semangat. Multi bahasa saya pelajari dengan sungguh-sungguh, hingga akhirnya saya bisa diterima kuliah di Kairo dengan gratis dan lulus empat tahun lalu.
Pernah suatu hari saya bertemu Karim di Kairo. Ia ternyata mendapat beasiswa juga dari Yayasan yang berbeda. Karim memelototi saya. Ia tidak tahu siapa orang yang sedang berada di hadapannya. Waktu itu sebenarnya saya tidak terlalu asing dengan wajahnya. Ketika saya mempertajam ingatan, apa-apa saja yang terjadi masa-masa kami di pesantren, sontak saya teriak “Si Celana Calattong” dan bergegas memeluknya.
Ia baru sadar ketika saya memperkenalkan diri. “Astaga, kau ternyata di sini juga Hanafi. Bagaimana keadaaanmu di sini?”
Saya tidak banyak basa-basi. Saya bilang kalau saya kuliah dan dapat beasiswa. Lalu kami berdua pun saling tukar pengalaman. Katanya, “Kau tahu si Abdul sekarang? Ia juga di sini. Sama seperti kita.”
“O, ya? Bagaimana keadaannya?”
“Sambil kuliah ia jualan sate. Satenya laris manis.”
“Agaknya Si Abdul punya nasib mirip dengan saya. Sambil kuliah saya juga jualan. Jualan nasi kobel. Lumayanlah buat tambah-tambah biaya hidup.”
Karim pun nampaknya sama. Ia juga bekerja sambil lalu kuliah. Di dekat kampus, di sebelah kafe ada sebuah masjid. Di sanalah ia bekerja, mengajar ngaji anak-anak yang kurang mampu.
Murid-murid di kelas ini terlihat serius. Lalu si Andik, murid yang suka bercanda tiba-tiba mengacungkan tangan seraya bertanya, “Kalau jualan sate di Kairo pembelinya orang Madura, pak?”
Murid-murid jadi tertawa terkekeh-kekeh. Saya pun ikut tertawa. Dengan sedikit mengembalikan otot-otot muka yang bergeser karena tawa, saya berusaha menetralkan keadaan, “Sate Madura itu, anak-anak, cocok untuk semua lidah. Jadi, siapa pun itu pasti akan suka dalam sekali coba.”
Ya, begitulah si Abdul, anak penjual sate yang pernah saya tonjok pipi kirinya di pesantren, kini sudah menjadi pengusaha sate dan buka cabang di mana-mana.
“Kalau Bapak pernah sekolah di Kairo, kenapa Bapak mau mengajar kami?” celetuk si Andik lagi.
“Karena ingatan. Karena ingatan tentang pesan bapak saya.”
“Kok bisa ingatan, pak?”
Saya tidak menjawab. Saya merenung dan sekelabat ingatan bermunculan di kepala saya. Tentang bapak, tentang Ustadz Damhuri, tentang kepala botak, dan tentang pelajaran-pelajaran yang saya dapat di pesantren yang membawa saya menjadi guru di tempat terpencil ini, sebuah pulau kecil yang jarang diperhatikan pemerintah.
Demikianlah, mungkin memang begitu cara kerja ingatan.
- Calattong: dalam bahasa Madura berarti kotoran sapi.
- Nasi kobel: nasi santan, biasanya dibubuhi abon dari ikan laut dengan lauk ikan tongkol, bisa di dapat di daerah pesisir Sampang.
Baca Juga: Bayangan masa depan
| BekelSego adalah media yang menyediakan platform menulis. Semua karya tulis sepenuhnya tanggung jawab penulis. |