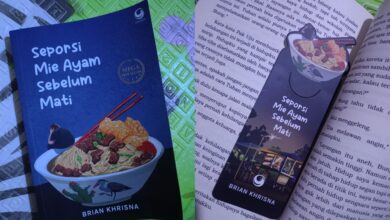Tak ada yang lebih diinginkan ayah, selain makin banyak saja orang yang mati. Sebab dengan begitu maka dia bisa membungkam mulut rewel ibuku, mulut rewelku, dan adikku juga. Sebab dengan begitu maka ibu tak akan sering ngedumel sendiri di dapur, sambil memasak air panas yang tak pernah ada isinya. Sebab dengan begitu, aku tak akan berteriak-teriak lagi karena sepatuku sudah terlalu usang untuk dibawa sekolah. Sebab dengan begitu juga, adikku tak akan menangis diam-diam karena baju bonekanya sudah terlalu lusuh.
Aneh memang, tapi begitulah ayahku. Seorang penggali kuburan. Jadi dia mengais uang dari jumlah orang yang mati. Semakin banyak orang mati, semakin tebal kantong celananya. Semakin tebal kantong celananya, semakin bisa juga ia mengurangi teriakan-teriakan meminta anggota keluarganya. Yaitu, aku, ibuku dan adikku.
Sudah dua hari ini, ibuku terus-terusan mengomel. Katanya ayah tak seperti yang dulu. Ayah yang dulu pernah janji, kalau mau menikah dengannya maka semua kebutuhan ibu bisa terpenuhi. Ayah juga menjanjikan harta, kesenangan dan masa depan bahagia.
“Tapi apa?”, kata Ibu sambil mendengus diantara asap air mendidih. “Apa bahagia itu kalau hanya tinggal di gubuk reyot seperti ini. Apanya yang senang, kalau untuk makan daging saja harus menunggu jatah Qurban setahun sekali. Mana masa depan bahagia itu, kalau bayaran sekolah anak tak selalu nunggak?”, cerocos Ibu tak henti-henti.
Ayah cuma bisa terdiam, kalau Ibu sudah marah seperti itu. Mungkin dia teringat petuah orang tuanya, yang pernah diceritakan kepadaku. “Kalau perempuanmu marah, kamu harus tetap sabar. Hidup berpasangan itu harus seperti air dan batu. Jangan keduanya menjadi batu. Kalau dua-duanya jadi batu, bisa hancur kalau berbenturan”, begitu kalimat petuah yang diteruskan turun temurun, dari kakek ke ayah, kemudian kepadaku.
Kalau sudah begitu aku hanya diam saja. Berpikir keras, bagaimana ayah mau membelikan sepatu baru untukku. Sepatu itu sudah terlalu jelek. Sol bawahnya hampir tak bisa menempel lagi, karena sudah berulang kali ditempel dengan berbagai lem. Ujung-ujungnya karena robek terus, kujahit sol sepatu itu. Jadinya malah makin rusak, karena bahan sepatu sudah terlalu tipis.
Sekarang aku hanya memakai tali sebagai penyambung nyawa sepatuku. Kuikat melingkar dua kali ke atas dan ke bawah. Seperti pemain bola saja, kalau mengikatkan tali sepatu. Tapi masalahnya, ujung depan sol tak mau bekerjasama. Ujung itu membuka terus, sampai akhirnya kubebat saja dengan isolasi lakban.
Jadilah sepatuku barang paling aneh di seantero kelas sekolah. Jadi barang bercanda teman-teman yang lain. Awalnya aku cuek saja, tapi semenjak Ilas, perempuan gebetanku juga ikut tertawa-tawa senang kalau sepatuku jadi bahan bercanda, aku jadi tak bisa menahan hati. Ilas itu tak pernah tertawa lebar semenjak aku kenal dengannya. Dia perempuan paling muram didalam kelas. Tapi kemuraman itu tak menghilangkan rona senja dimatanya. Senja yang sanggup membuat terik matahari siang menjadi redup, kala sedang berjalan bersama sepulang sekolah.
Suasana redup itu yang terasa akrab dihati. Seperti suasana redup disekeliling rumahku, yang penuh dengan kuburan. Suasana redup yang membuat Ilas seperti tak asing dimataku. Suasana redup yang terasa memang Ilas adalah bagian dari hidupku, sejak dulu aku dilahirkan.
“Kamu jangan ikut-ikutan menertawai kalau Indro sedang komentar tentang sepatuku”, kataku kepada Ilas, pada suatu siang.
“Habis, sepatumu lucu”, Ilas menjawab sambil tertawa lagi.
“Lucu gimana?”.
“Benar kata Indro, kayak buaya mangap”.
Sialan, kata hatiku. “Pokoknya kalau kamu tetap menertawaimu, aku nggak mau lagi pulang sekolah sama kamu”, kataku menggertak.
Ilas bukannya takut, malah membalas lebih nyeri lagi. “Yah sudah, lagipula siapa suruh pulang bareng terus. Lagi juga aku malu pulang bareng sama cowo yang sepatunya aneh kayak gitu”.
Sial, sial, pikirku. Kenapa sih ayah tidak mau membelikan sepatu baru saja. Apa susahnya sih, sepertinya membeli sepatu baru harus merelakan barang paling berharga miliknya. Padahal ayah tinggal berdoa saja. Berdoa agar ada orang yang mati.
“Hush…tidak boleh begitu”, kata ibuku. “Doa agar orang mati itu keramat. Itu cuma keluar kalau suasana terdesak”, ujarnya, pada suatu sore usai kulihat adikku kembali merengek minta dibelikan baju boneka baru.
“Sekarang kan kita sedang terdesak bu”, balasku.
“Terdesak apa?”.
“Itu, Ibu nggak punya uang buat makan. Adek nggak bisa beli baju baru buat boneka. Aku sendiri nggak bisa punya sepatu baru”.
Sambil tersenyum Ibu menggeleng. “Terdesak itu, kalau ada seorang dari kita ada yang sakit. Perlu obat, tak punya uang. Baru mungkin doa itu bisa keluar dari mulut ayahmu”.
“Jadi harus sakit dulu nih?”, tanyaku jahil.
“Jadi kamu mau sakit?”, balas Ibuku tak mau kalah.
Aku menggeleng. Siapa juga yang mau sakit. Kalau dipikir-pikir mending tak pakai sepatu baru, daripada harus merasakan sakit.
Aku melangkah lagi, menuju ke kamar ayah sering beribadah. Kulihat ia sedang khusyuk berdoa. Menundukan kepala sambil mulutnya komat-kamit. Peci dikepalanya sudah terlihat kusam. Baju kokonya juga sudah robek dibagian leher belakang.
“Ayah”, panggilku pelan, setelah duduk bersila dibelakangnya.
Tak ada balasan darinya. Dia terus menunduk dan berkomat-kamit. Sepertinya membaca doa, dengan kalimat-kalimat yang kurang aku mengerti. Mungkin bahasa-bahasa Arab, tapi tak pernah kudengar sebelumnya bila Ayah membacakan doa usai sholat bersama.
“Amiiinnnn…”, suaraku agak ku keluarkan keras-keras, agar Ayah mau menengok. Benar saja, tak sampai dua kali aku berbicara keras, kepala Ayah sudah mencari ke belakangnya. Ketika melihatku, ia hanya memandang dengan heran. Lalu matanya menyiratkan agar secepatnya aku enyah dari hadapannya.
“Ajarkan aku doa meminta kematian”, kataku berusaha tegas.
Mata Ayah mendelik. Kemudian tubuhnya berputar menghadapku. Memandang kembali seakan tak percaya. Mungkin dia pikir aku sudah gila.
“Aku tidak gila”, suaraku menyembur berusaha tidak membenarkan apa yang kupikirkan tentang pandangan Ayah.
Kepala Ayah menggeleng. Tumben ia tidak berbicara keras kali ini. Bukan kali pertama ini, aku merajuk diajarkan doa meminta kematian. Sudah sudah puluhan kali, tapi selalu dijawab dengan suara keras oleh Ayah. Katanya aku belum cukup umur, belum siap menghadapi resikonya, belum mampu menjalankan syarat-syaratnya, belum tahan dengan ujian-ujiannya, dan seribu alasan belum-belum yang lain lagi.
“Aku sudah 17 tahun sekarang”, suaraku memastikan. Memberi penegasan kalau umur segitu seharusnya sudah dianggap dewasa.
“Memang apa urusan yang mendesak sampai kau minta diajarkan doa itu?”, kata Ayah akhirnya.
“Aku mau beli sepatu baru. Kalau tidak aku bisa ditinggalkan Ilas. Berarti aku tak punya masa depan lagi. Apa itu tidak mendesak?”, jawabku sambil mendengus.
Ayah cuma tersenyum. Dia sudah tahu perkara sepatu baru dan Ilas. Ibu pasti yang bercerita padanya.
“Jodoh tak bisa dipaksakan nak”, katanya pelan.
“Tapi jodoh harus diusahakan”, kataku tak mau kalah.
Ayah kembali hanya menggeleng. Mungkin ia ingat Ibuku yang tak mau kalah ngomong. Mungkin aku seperti Ibuku juga. Namun raut diwajahnya tetap menampakan penolakan. Naga-naganya aku kembali akan kecewa kali ini.
“Tapi aku akan meluluskan permintaanmu. Aku akan membacakan doa itu lagi. Mengingat kalian semua terus-terusan mendesak dengan rengekan itu. Itu membuatku menjadi terdesak”, jawab Ayah tegas.
Aku hampir berteriak bahagia. Berarti sebentar lagi akan ada lagi orang yang mati. Akan ada orang yang meminta ayahku untuk menggali kubur lagi. Akan ada uang lagi yang masuk kantong Ayah. Berarti juga, aku akan dapat sepatu baru, adikku akan dapat baju baru buat bonekanya, Ibuku akan tersenyum bahagia karena ada makanan yang bisa dimasaknya.
Besoknya seperti ritual biasa kalau mau membaca doa meminta kematian, Ibu akan ribet menyediakan ini dan itu. Termasuk mengambil bunga-bunga yang hanya tumbuh dikuburan, mengambil air yang mengitari area pekuburan, serta mengambil segenggam tanah di titik tanah area kuburan yang kosong.
Semua syarat-syarat itu ditaruh Ibu disebuah nampan berbahan perak. Kemudian ditutup dengan kain berwarna kuning, dengan renda-renda dipinggirnya yang berkilau serupa emas. Ibu juga menyuruh kami tidur cepat-cepat malam ini. Tak ada kata tidak. Tak ada juga yang bisa melanggarnya. Bahkan adikku yang menangis keras-keras lagi, karena tidak bisa menonton acara televisi kegemarannya malam itu.
Aku sih senang-senang saja, disuruh tidur cepat. Di kepala membayang aku memakai sepatu baru ke sekolah. Terbayang mulut Indro yang akan terbungkam. Terbayang bisa berjalan-jalan lagi bersama Ilas. Pasti akan menjadi sore yang cerah ceria. Ahhh…mimpi yang indah.
Tiba-tiba mataku membuka lebar. Ada suara-suara aneh dikamar bawah. Seperti ada yang berteriak-teriak disana. Tanpa menghiraukan larangan Ibu, aku segera berlari kesana. Ke kamar yang biasa Ayah berdoa. Disana Ibu tampak memeluk Ayah. Tubuhnya kaku.
Baca Juga: Sehangat Coklat Panas di Kota Dingin
BekelSego adalah media yang menyediakan platform untuk menulis, semua karya tulis sepenuhnya tanggung jawab penulis.