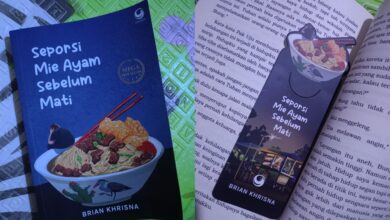Dari teras belakang rumah, pada sebuah bangku panjang dengan tanaman hias di sekitarnya Antonia dapat menatap keagungan semesta atas nama senja. Saat matahari perlahan menggelincir seakan bola raksasa merah menyala yang semakin memudar kemudian menyentuh batas cakrawala. Satu garis lurus yang kekal menyatukan kaki langit dan laut. Angkasa semburat merah diwarnai teja, bagai lukisan maha dasyat saat sekawanan burung mencecet terbang kembali pada rumah sesungguhnya.
Antonia selalu menikmati perubahan cahaya, saat terik terhuyung menuju padam, berguncang antara perubahan gelap dan terang. Senja ini seharusnya Antonia merasa damai, ia telah menginjak usia dua puluh tahun, menginjak dewasa di tanah Asmat –Tanah Leluhur, adalah hutan hujan yang mencurahkan air dari langit sepanjang tahun. Akan tetapi, senja ini ia dihantam rasa gamang. Ia tak dapat menolak pinangan Albertus, tetapi tak dapat pula duduk sebagai pengantin pada waktu dekat.
Ayahanda telah menyiapkan keberangkatan untuk pendidikan tinggi di ibu kota negara. Ia akan melayang di dalam lambung kapal udara jenis twin otter selama 45 menit ke Timika, bermalam di hotel kemudian terbang ke Jakarta menumpang pesawat Garuda dengan transit di Denpasar. Selebihnya ia akan bertarung dengan waktu untuk bisa mengenakan toga, kembali ke tanah leluhur dengan selembar ijasah di tangan dan kemampuan di pemerintahan yang memadai.
“Engkau harus menjadi dirimu sendiri, bukan sekedar ibu rumah tangga yang tergantung secara total kepada suami. Lihatlah hal terburuk yang terjadi setelah perkawinan, kekerasan di dalam keluarga terjadi, korban berikutnya adalah anak anak. Selamatkan dirimu, selamatkan seluruh keturunanmu,” kata kata ayahanda tiada yang salah.
Antonia yakin dengan kebenaran itu, karena ia sudah melihat kenyataannya. Ketika seorang laki laki selalu menempatkan otoritas di atas istri, merasa berwenang akan segala perintah dan dapat bertindak apa saja ketika seorang istri dianggap melakukan pembangkangan. Apa yang akan terjadi dalam perkawinannya bila ia hanya seorang bocah ingusan yang tahu apa apa, bahkan ketika harus melindungi diri sendiri dan anak anak yang harus dilahirkan? Akan tetapi, bagaimana ia bisa meninggalkan Albertus, pangeran impian yang melekat dalam ingatan, pagi, siang, dan malam.
Kehilangan Albertus berarti kehilangan masa depan. Ia sungguh takjub dengan penantian, kesungguhan, dan keberanian pemuda itu. Mampukah Albertus menunggu, atau ia harus menerima kekalahan pada suatu waktu ketika pendidikan selesai, ia telah bersiap bagi perkawiban itu, karena Albertus berpaling kepada pilihan lain. Antonia kini tahu arti rasa sakit dan kehilangan, ragu dan kekalahan. Seakan lapisan kulit dikupas secara paksa dari tulang belulang. Perpisahan berarti rindu tanpa ujung yang akan segera berubah menjadi lidah belati, menikam dan melukai. Ia harus menempatkan diri pada posisi yang amat meragukan, untuk mendapatkan atau melepaskan.
Langit merah seakan berlumuran darah ketika Antonia duduk termangu, terus menatap ke cakrawala. Pandangannya tak akan mampu menembus waktu, hari depan adalah misteri, tak seorang pun mampu menjawab tabiritu, kecuali dengan segala keberanian yang bersangkutan berkeras menjalani. Antonia tergagap ketika ponsel berdering, pada layar tertera nama Albertinus. “Halo,” dengan sigap Antonia menjawab.
“Antonia, kutunggu di dermaga ….” Suara berat Albertus seakan bergema hingga jauh ke relung hati.
“Baik, tunggu,” Antonia segera beranjak ke dalam kamar, mengganti pakaian, merias diri sekedarnya, mematut-matut di depan cermin. Langkah gadis itu seakan terbang ketika berjalan menuju ke dermaga, tempat ia biasa bertemu Albertinus. Mama sibuk di dapur, ayahanda ada bincang-bincang dengan seorang tamu di ruang keluarga. Ia bisa menyelinap pergi, tanpa menimbulkan kegaduhan dan pertanyaan.
Di dermaga Albertinus tengah duduk menunggu, tatapannya melayang jauh hingga ke batas langit, di bawah semburat matahari senja, wajah itu seakan bermandikan cahaya jingga. Hati pemuda itu sungguh galau, ia pernah ditinggalkan seorang gadis dengan alasan belajar ke ibu kota, setelah menunggu ternyata gadis itu tak pernah kembali, hanya datang berkunjung bersama suami dan seorang anak. Ia pernah dikhianati, ia pernah kesakitan, karena kalah telak dengan memalukan. Kini, haruskah ia menelan kekalahan yang sama, setelah melepaskan Antonia pergi, maka gadis itu tak akan pernah kembali.
“Albert ….” suara Antonia lembut, ia menyentuh pundak pemuda itu kemudian duduk di sampingnya, menyisakan kesiur angin sebagai jarak. Ia dapat menangkap wajah muram Albertus itu, wajah yang penuh harap, ketakutan, sekaligus memendam amarah jauh di kedalaman.
“Engkau jadi berangkat?” suara Albertus serak.
“Besok pagi,” Antonia mencoba menguasai diri, ia tahu Albertus sungguh meragukan keberangkatan ini.
“Benar, engkau akan kembali?”
“Engkau masih tidak percaya, aku pergi bukan untuk berpaling, tapi untuk menimba ilmu. Orang tua ada di tanah lumpur, aku pasti kembali.”
“Dulu, Margaretha berpamit menimba ilmu, orang tuanya juga menetap di tanah yang sama, tapi ia tak pernah kembali. Ia hanya datang berkunjung bersama anak dan suami. Ia pergi selamanya, adakah engkau akan melakukan hal yang sama?” lidah Albertus terasa pahit, andai ia bisa membawa Antonia berlari ke suatu tempat yang tidak memerlukan pendidikan, hanya ia dan Antonia.
Zaman telah berubah, ibunda adalah seorang yang hanya tahu berkebun, melahirkan tujuh anak, tiga meninggal, ayahanda pegawai di kantor distrik. Bersyukur ia pernah melewati proses pendidikan, sehingga ia kini seorang guru. Ia tidak perlu pergi ke hutan milik ulayat untuk memangur sagu dan menjaring ikan demi upaya pertahanan hidup, ia mendapatkan penghasilan yang ditransfer setiap bulan. Ia bisa pula berbagi uang saku bagi ibunda, seorang perempuan yang cepat menua, seorang yang mengalami kekerasan di dalam keluarga, karena tak memiliki bekal pendidikan yang cukup, posisi di dalam birokrasi, transfer setiap bulan ke dalam rekening di Bank Pembangunan Papua, jumlah uang yang dapat dihemat untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidup.
Kecuali harus mengerjakan seluruh urusan rumah tangga, ibunda tak berdaya apa-apa, ketika ayanda memukul, bahkan mendatangi perempuan muda sebagai istri kedua dan ketiga. Albertus tahu, mengapa Antonia harus berpamit menimba ilmu, gadis itu –atas dukungan ayahanda tidak ingin mengulang kesalahan sama, ketika menjelang perkawinan seorang perempuan mesti kehilangan otoritas, karena tidak berdaya apa-apa, kecuali mengerjakan urusan rumah tangga. Antonia perlu menjadi kuat sebelum perkawinannya.
“Aku bukan Margaretha, aku Antonia, tak akan kujilat ludah sendiri. Aku berpamit, tapi untuk kembali,” Antonia menggenggam tangan Albertus, telapak itu menggigil, beku. Dada Antonia terasa sesak, diam-diam ia merasakan ketakutan yang sama. Bagaimana bila pendidikan selesai, ia kembali berharap akan sebuah hari bahagia, tetapi Albertus telah menjelang hari bahagia bersama pilihan yang lain. “Atau yang akan terjadi bahkan sebaliknya, bila pendidikanku selesai, aku kembali dengan harapan, tetapi justru engkau yang berpaling?” lidah Antonia tak kalah getir, andai Albertus benar berpaling, karena tak kuasa menunggu. Ia akan memerlukan tahun-tahun panjang untuk melupakan, ia akan mengalami luka permanen tak tersembuhkan. Apa pilihannya kini, kecuali tetap berangkat menimba ilmu dengan kemungkinan paling buruk yang mungkin terjadi, diabaikan.
“Ke tempat mana aku harus berpaling?” Albertus membuang pandang sejauh mungkin, senja bergoyang pada perubahan cahaya, menuju temaram. Tanpa mendung, langit membentang luas tak berkesudahan, matahari dengan pasti bergerak turun menuju kaki langit, bersiap menghilang, seakan hendak membenamkan diri jauh hingga ke dasar lautan, menyisakan malam. Sepasang mata Albertus terus menatap tak berkedip. Andai ia bisa menahan matahari untuk tetap berpendar pada selamanya langit senja, andai ia bisa hanya berdua saja dengan Antonia, tanpa kehadiran siapa-siapa, juga tatanan nilai yang menyebabkan seorang perempuan harus berpendidikan tinggi, memiliki status sosial, dan profesi sebelum menikah, yang konon justru menimbulkan musuh di dalam selimut.
Hening terpecah oleh dering seluler, Antonia menatap foto ayahanda pada layar, ia tahu, pertemuan dengan Albertus berakhir sudah, ia tak mampu mengelak dari panggilan ayahanda, dering seluler itulah buktinya. “Halo, iya bapa, saya pulang ….” Antonia hafal dengan suara ayahanda saat ia pergi meninggalkan rumah hingga senja semakin redup menuju petang. Ia harus pulang.
“Aku berpamit, besok harus pergi. Bila engkau akan menyertai ke Bandara Ewer, datanglah,” mata Antonia telah tergenang, akan segera mengombak menjadi sepasang danau kembar andai ia gagal menahan sedu sedan. Ia harus kuat. Ia ragu saat melepaskan genggaman tangan Albertus, tetapi harus. Tanpa pendidikan tinggi, ia tak akan sanggup menatap masa depan, hari-hari panjang berselubung kabut misteri yang harus disingkap untuk seluruh takdir hidup.
Di langit sebelah barat dengan perlahan, namun pasti bola matahari telah menyentuh batas kaki langit, jarum jam terus bergerak pasti, senja benar mengelam, berubah warna menjadi malam ketika seluruh cahaya sirna di balik garis samudera. Esok akan terbit kemudian terbenam matahari yang sama, dalam menawan cahaya senjakala.
Hutan Hujan, 6 Maret 2023
Baca Juga: Emma Bersama Ayah