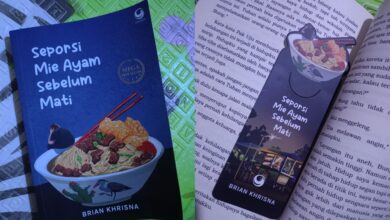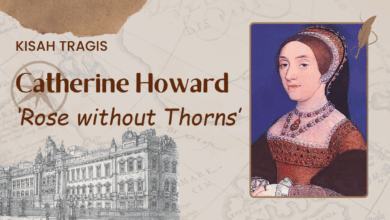Setiap hari saban sore datang, aku selalu berkelit mencari alasan yang tepat tentang kesetiaan yang pernah aku janjikan sebelumnya. Orang-orang di sawah sering menghardikku dengan bahasa relatif elegan. Muka mereka dipenuhi lumpur. Aku tetap meniup seruling menunggu senja angslup di ufuk.
Ketahuilah, Alzela, aku tak pernah punya pikiran lain di sana. Aku hanya mencoba memahami siapa diriku sebenarnya. Hanya seruling yang mengerti maksudku itu. Tak ada yang bisa memahami siapa aku yang membuat orang-orang harus berpikir beberapa kali untuk mengajakku mengawali temaram.
Alzela, cerita tentang orang-orang di rawa ini terlalu rumit untuk kusemayamkan sendiri di dalam pikir ini. Ia menyayat hati, membentuk sebuah kubu yang mengijinkan semua orang menghardik sesama. Sedang padi tak kunjung tumbuh. Irigasi kurang baik. Dan persediaan makanan semakin tipis. Sungguh menyebalkan.
Aku melihat Surga di sini, Alzela. Surga yang tak pernah mau dirawat kaum-kaum pecinta alam. Mereka mencintai alam dengan menghabiskan seluruh pohon-pohon mahoni. Padahal pohon itu sangat kusuka. Pohon itu yang membuat hati menjadi tenang. Yang membuat aku terus menulis cerita tentang orang-orangan sawah yang tak lagi mempunyai fungsi etis. Tak ada lagi yang perlu ditakuti dari burung-burung pemakan padi, dari hama yang selalu mematikan dan membuat para pakar Pestisida memiliki pekerjaan yang menjanjikan dengan formula-formulanya yang akurat karena ilmu disiplin yang tinggi.
Alzela, aku takut. Bawalah aku ke negerimu. Bukankah engkau dulu yang pernah mengajakku pergi dari negeri sawah ini? Jawab aku Alzela. Jawab aku dengan “Iya”. Aku mohon Alzela, jangan biarkan aku tertunduk di sini mengibaskan kesedihan menjadi angin yang tak punya musim. Saban sore aku menjadi risau akan wajah negeri yang berseri penuh harap semerbak.
Jadilah pahlawanku, Alzela. Benar-benar runyam hari ini otakku menghadapi kota. Aku menangis dalam siul yang tak mau mengiringi. Tak ada irama sama sekali di sini. Hanya hardik, Alzela. Hanya hardik yang terus mencabik.
Kemarin pagi, sebuah surat kabar datang menamu dengan sendirinya ke beranda rumahku. Ia bercerita tentang kotamu yang semakin hari, semakin menyunggingkan senyum. Kota, Alzela selalu memilki stok kebahagiaan yang tak kunjung habisnya. Aku benar-benar ingin ke sana. Akan kubawa kesedihan ini ke meja makan Resto yang pernah kau ceritakan padaku. Ya, Rumah Makan itu pun termaktub dalam surat kabar itu. Katanya, di sana banyak orang-orang yang sekedar duduk menghabiskan uang mereka dalam sekali saji. Aku akan ke sana, Alzela. Aku akan ke sana. Kirimkan Surat untukku. Kirimkan alamatmu.
***
Aku benar-benar bimbang. Surat itu datang juga setelah sekian hari aku tunggui. Orang-orang sawah itu tak akan menghardikku lagi. Siapa suruh mereka menghardik orang yang ingin melukiskan Mahoni yang pahit. Habis betul sudah harapanku di sini. Aku harus pergi. Sudah bulat tekad ini untuk menemui Alzela. Semoga percakapan tak hanya menyisakan tinta dan kertas yang berserak.
Manakala mata terbangun pagi-pagi. Buru-buru aku menyiapkan perbekalan. Buras yang berikat-ikat, sabal, dan sebuah tas ransel yang setia menjadi teman perjalanan. Hanya satu yang kutinggalkan : sebuah topi bundar, pemberian Ayah. Biar topi itu yang menjaga rumah. Toh rumah tak ada penghuninya.
“Aku bawakan untukmu, Alzela : sebuah pengharapan yang tersimpan dalam kelam.”
Sebuah pintu yang pernah menjadi tanggungjawabku dulu. Kini harus kutitipkan pada topi bundar itu. Sebab hanya ia mengerti diriku. Aku harus segera pergi. Perahu sudah menunggu di tepian. Untung Suparman, pemilik perahu itu adalah orang yang bisa memahami kepedihanku selama ini. Satu-satunya orang yang mau mendengar ceritaku tentang Alzela yang cantik rupawan.
Melautlah aku ke kotamu. Sebuah pertanda akan datang kebahagiaan. Di mana aku akan menemukan rupa kau yang sesungguhnya. Rupa penulis yang sangat aku impikan bisa bersanding bersama di pelaminan. Sungguh ini hari, hari yang baik.
“Mengapa kau tersenyum sendiri Alimin?”
“Tidak, aku tidak sedang tersenyum sendiri Suparman. Aku akan pergi ke sebuah kota dambaan semua orang. Kau tau, Suparman, di sana aku akan menemui siapa?”
“Alzela?”
“Ya, tepat sekali, kau memang selalu tepat membaca isi hatiku.”
Aku melihat Suparman menggelengkan kepala. Entah apa yang dipikirkan. Ia selalu begitu jika kuceritakan tentang Alzela : menggeleng dan tersenyum.
Laut semakin luas. Pulau tak lagi terlihat. Seikat buras aku buka. “Simpul mati?” Suparman bertanya dengan nada heran. Aku hanya tersenyum. Hanya simpul ini yang aku bisa. Sebelum aku menjadi seorang penganggur. Aku pernah sekolah di salah satu Sekolah Dasar. Tapi tidak tamat. Hanya itu yang kudapat dari sekolah itu.
Kami berdua bercakap dengan hikmat. Sambil sesekali menyesap kopi yang telah dikudeta oleh penguasa dingin. Melaut dengan tenang. Merumuskan suasana senang di kota nanti.
***
Sebuah dermaga yang begitu asing bagiku. Anak-anak ingusan datang mengelus pundakku dan membisikkan sesuatu padaku. Aku tak mengerti maksudnya. Ia menggunakan bahasa apa. Aku bertanya-tanya. Siapa anak kecil ini. Tapi, tidak. Anak kecil itu tak sendiri. Tapi mengapa ia kumuh sekali? Aku dihantui kecurigaan. Ah, Alzela, sudah menunggu. Tak mungkin aku akan menyia-nyiakan waktuku hanya untuk memikirkan anak kecil ini.
Orang-orang di kota ini sungguh ramah. Mereka berbondong-bondong menawari aku sebuah tumpangan. Tapi, aku menolak. Aku ingin berjalan saja. Kata orang-orang sawah, kota punya banyak kebahagiaan, pun Alzela senada dengan itu. Aku tak boleh menyia-nyiakan itu.
Benar pula. Aku melihat orang-orang yang berdiri di depan trotoar menghadap ke timur. Ia seperti sedang melaksanakan upacara. Ia hormat sendiri. Sungguh kota sangat menakjubkan. Pantas orang-orang sawah tak mau ke sini. Orang-orang sawah kan orang-orang kolot.
Hatiku semakin semerbak. Ada yang terlupa menjelang sore. Ternyata perutku belum terisi sesatu pun makanan. Perbekalan sudah habis. Suparman sudah kembali. Aku harus pergi mancari Rumah Makan dalam surat kabar tiga tahun yang lalu. Mungkin itu akan membantu. Aku bertanya pada tukang becak tentang itu. Tapi tak ada jawab. Tak ada yang mau membukakan pintu hatinya memberi petunjuk walau hanya satu petunjuk arah.
Aku menjadi ragu. Mana mungkin Rumah Makan yang terkenal itu, tidak dikenal tukang becak di sini. Bukankah memilih pekerjaan menjadi tukang becak harus mengetahui seluruh isi kota. Tapi, tak apa. Mungkin tukang becak itu tidak bisa membaca. Aku tidak terlalu paham dengan tukang becak. Jadi, tak perlu aku khawatirkan tentang itu. Setidaknya, mereka menunjukkan padaku sebuah warung kopi.
Benar kata koran itu, kopi di kota ini, sangatlah nikmat dan beraneka. Aku tak tahu harus menjawab apa pada pemilik warung ketika ditanya ingin memesan apa. Kujawab saja sekenanya, “ Terserah, bu. Asalkan aku bisa menyesap nikmatnya kopi kota.”
Terjawab semua keraguanku. Tukang becak itu memang tidak sekolah. Tapi, seorang guru yang kutanyai tentang Rumah Makan itu pun tak mau menjawab.
“ Surat Kabar itu terbitan tiga tahun yang lalu, bukan?”
Aku hanya tersenyum dan menunduk. Mungkin benar, Rumah Makan itu sudah tak ada lagi dalam riwayat kota ini. Mungkin sudah dihapuskan namanya. Atau mungkin benar-benar tak ada. Aku tak perlu memikirkan itu. Tak perlu. Ya, kurasa memang tak perlu.
***
“ Tapi, Alzela. Mengapa semua ini tak sesuai dengan suratmu? ”
Siapakah kau sebenarnya Alzela? Sudah berhari-hari aku mencari alamatmu. Tak kutemui satu pun cahaya menuju pintu rumahmu. Alzela, perbekalanku sudah menipis. Aku ingin pulang. Kembali ke kampungku, menemui orang-orang sawah, meniup seruling, dan menjadi petani seperti mereka. Semua waktuku sudah tersia. Terimakasih atas semua ini. Alzela, kutuk aku. Kutuk aku dengan seluruh risalah, surat kabarmu.
**
Baca Juga: Misteri Kamar Mandi