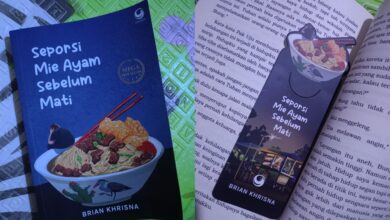Aku berjalan menuju ruang kelasku, dengan satu cup mie goreng ekstra pedas dan kentang goreng di kedua tanganku. Sesekali ku lirik jam tangan abu-abu yang melingkar cantik di sebelah gelang kayu berukirkan ‘Natya’, hadiah dari mendiang ayahku. Koridor panjang ini memaksaku untuk mengambil langkah besar-besar untuk mencapai ruang kelasku yang berada di ujung sana. Sebetulnya malas rasanya pergi ke kantin, mengingat jaraknya dari ruang kelasku yang sangat jauh itu.
Hari ini adalah hari pertama kami mengikuti les sepulang sekolah. Aku ingat betapa Bu Ratna, guru kami, selalu mengingatkan kami untuk membawa bekal makan siang. Sekarang pertanyaannya adalah, siapakah yang akan menyiapkannya untukku? Mama selalu berangkat pagi-pagi buta untuk mengejar keretanya. Ia adalah guru di salah satu SMP di perbatasan kota. Dan ia tidak pernah benar-benar peduli padaku. Untuk itulah aku lebih sering menginap di rumah nenek..
Sesampainya di ruang kelas, aku segera membuka mie yang baru saja kubeli dan memakannya, teman-teman pun begitu.
“Aku lihat ‘dia’ lagi.” Tiba-tiba Siska menoleh dan mulai membicarakan berita bodoh itu lagi.
“Di tempat itu lagi?” yang direspon dengan semangat oleh Rini, teman sebangkuku yang entah mengapa jauh lebih nyambung saat berbicara dengan Siska, meskipun kami sudah duduk sebangku selama hampir tiga tahun.
Siska menggeleng dramatis, “Di depan gudang, yang dekat kaca.” Ia menjawab dengan wajah seriusnya.
“Nggak heran sih, gudang kan deketnya kamar mandi,” ucap Rini. “Lihat, Nat. Masih nggak percaya?” ia menanyaiku. Aku hanya mengangkat bahuku acuh, masih sibuk memunguti potongan daun seledri kecil-kecil dari mie gorengku.
“Kenapa kamu jadi ikut-ikutan bahas si ‘dia’ sih? Setahuku kamu nggak percaya,” tanyaku pada Siska. Sedetik kemudian kedua kawanku itu saling beradu tatap sebelum akhirnya melanjutkan makan siang mereka dalam diam. Aku SANGAT tidak percaya pada hal mistis semacam itu. Lagipula hanya orang bodoh yang mempercayainya. Jadi, apakah aku jahat dengan mengatakan bahwa hanya sebagian kecil saja siswa di sekolah ini yang pintar?
Di sekolah ini, semua orang tahu si “dia” yang baru saja dibahas Siska dan Rini. Singkatnya, dia adalah hantu, atau orang-orang lebih sering menyebutnya sebagai arwah. Ada beberapa versi cerita tentang si arwah, yang sebenarnya masih mirip-mirip. Ceritanya sangat klise sehingga aku berpikir bahwa mitos ini tidak seharusnya begitu dipercaya. Sependek yang aku tahu, si ‘dia’ ini adalah korban pembunuhan sadis yang mayatnya di kubur asal di dekat sini. Katanya, ia bisa menampakkan diri dengan wujud yang berbeda-beda, tetapi lebih sering terlihat sebagai seorang wanita dengan wajah rata. Alih-alih siswa popular atau berparas menarik, hantu itu justru lebih sering dibicarakan oleh siswa-siswi di sekolah ini. Dan aku? Selama hampir tiga tahun bersekolah di sini, bahkan selama 18 tahun hidupku, aku tidak pernah melihat hantu. Maka dari itu aku begitu yakin bahwa makhluk halus hanyalah mitos tak berdasar buatan orang-orang bodoh.
Hanya beberapa detik sebelum aku beranjak dari kursiku, Seorang pria paruh baya dengan kacamata bertengger malas di hidungnya memasuki kelas, Namanya Pak Prapta. Guru matematika baru kami yang baru dua minggu ini mengajar, menggantikan Bu Laksmi yang baru saja pensiun. Setelah menjelaskan materi hari ini, ia segera membagikan dua lembar soal kepada kami semua. Kenapa semua guru sama menyebalkan?
Sepuluh menit terakhir, tanganku basah dengan keringatku sendiri. Sial, aku sudah tidak tahan. Pak Prapta masih sibuk mengawasi kami yang juga sibuk ‘dikerjai’ soal-soal ini. Aku melirik jam tanganku sembari menghitung mundur sepuluh menit terakhir sebelum kelas sore ini berakhir. Sepuluh menit paling menyiksa di hidupku. Aku tidak lagi bisa fokus pada barisan angka-angka nakal di hadapanku ini. Aku masih berusaha memasang wajah normalku sembari meremasi ujung seragamku. Kenapa lama sekali? Aku bisa mati muda.
“Saya rasa cukup untuk hari ini, Besok kita lanjutkan materi tentang matrix,” adalah kalimat yang sejak tadi ku nantikan. Setelah melihat punggung Pak Prapta menghilang, aku segera berlari menuju kamar mandi tanpa menghiraukan pertanyaan-pertanyaan Rini yang lebih pantas disebut teriakan itu. Untungnya, kamar mandi ini dekat dengan ruang kelasku.
“Ah sial!” ku rutuki nasib buruk yang menimpaku bertubi-tubi ini. Semua pintu kamar mandi tertutup, yang k uasumsikan semuanya sedang digunakan. Tapi tak apa, akan kupertaruhkan kembali nasib baikku. Ku ketuk pintu-pintu kamar mandi ini satu persatu, karena, kenapa tidak? Siapa tahu ada satu kamar mandi yang tersisa untukku.
“Halo, apa ada orang di dalam?”
“Jangan dibuka,” teriak suara perempuan dari kamar mandi pertama.
“Halo, apa ada orang di dalam?” ku ketuk pintu kedua, ketiga, keempat, dan kelima, tapi aku selalu mendapat jawaban dari dalam. Fix, hari ini adalah hari sialku. Harapan terakhirku adalah kamar mandi terakhir di ujung ini. Aku sudah mempersiapkan diri jika mendapat teriakan dari dalam. Tapi beruntungnya aku, tidak ada yang merespon ketukanku. Aku segera membuka pintu itu. Akhirnya aku bisa bernapas dengan lega setelah rentetan drama hari ini.
Setelah selesai menggunakan toilet, aku mencoba membuka pintu kayu berwana coklat ini. Satu kali, dua kali, tiga kali. Sudah tak terhitung berapa kali aku menekan knop pintu ini, tetapi pintu tak kunjung terbuka. Apa ya yang salah? Pikirku. Kali ini aku mencoba mendobrak pintu di hadapanku itu sembari berteriak meminta tolong. “Apa terkunci dari luar?” gumamku sembari masih menekan knop, mendobrak pintu, dan berteriak berulang kali.
Ku hentikan kegiatanku sesaat setelah menyadari sesuatu. Apakah ini ruang yang selalu dihindari itu? Aku bahkan tidak berani membayangkan mitos-mitos yang selama ini beredar di sekolah, terutama tentang toilet perempuan. Aku bersusah payah menelan ludah. Ruangan dua kali dua meter ini gelap dan pengap. Langit-langitnya sangat tinggi dan tidak ada ventilasi udara yang cukup lebar, kecuali satu yang di atas pintu itu. Aku berbalik sehingga punggungku menempel sempurna di daun pintu. Jantungku berdegup tak karuan mendengar kesunyian yang sangat keras ini. Tidak ada lagi suara keran air dari bilik kamar mandi sebelah. Pun tidak ada suara pintu yang dibuka atau ditutup. Sangat sunyi.
Tuk… bola mataku dengan cepat menatap bak mandi di sebelah kiriku ini. Aku akui, aku sangat takut saat ini. Bahkan tetesan airpun bisa mengagetkanku. Gambaran tentang kemungkinan-kemungkinan terburuk menari-nari di pikiranku. Tidak mudah meyakinkanku sendiri bahwa semuanya pasti akan baik-baik saja. Aku terus bertanya hal-hal bodoh seperti, “bagaimana kalau ‘dia’ muncul dari bak ini?”, “bagaimana kalau ‘dia’ menatapku sekarang?”, dan pertanyaan bagaimana kalau bagaimana kalau lainnya.
Ku tutup kedua telingaku rapat-rapat. Keheningan ini begitu menyiksa. Aku tidak berani bergerak seincipun. Mataku masih menatapi sekitar. Aku bahkan hafal dengan bentuk noda coklat di atas bak mandi itu, bentuk sarang laba-laba yang tergantung di pojok kanan sana, atau bongkahan lantai keramik tidak simetris di dekat saluran air itu. Tunggu, sudah berapa lama aku di sini? Ku dekatkan tangan kiriku ke wajah untuk mengamati jam abu-abu itu dengan seksama. Pencahayaannya sangat buruk dan semakin memburuk. Sialnya lagi, saklar lampunya ada di luar. Tidak ada kemungkinan bagiku untuk menyalakan lampu kecil yang tergantung mengejek di atas sana. Gawat, sudah jam lima lebih seperempat. Aku bergidik sendiri membayangkan aku akan berdiri seperti ini, di sini, sepanjang malam ini. Tapi tidak akan. Pak sekuriti pasti akan mengecek semua sudut sekolah sebelum benar-benar menutupnya, kan?
Aku menutup penutup kloset dan duduk di atasnya. Gerakan paling berani yang aku ambil sejauh ini. Selama lima menit dalam posisi ini, aku mulai terbiasa. Lihat, tidak ada hal buruk yang terjadi padaku. Aku hanya harus menunggu sedikit lagi sampai sekuriti menemukanku. Ku tajamkan pendengaranku dan suara langkah kaki dari kejauhan terdengar. Ah, pasti sekuriti. Satu menit berlalu, dua menit, tiga menit, namun tidak ada perubahan yang berarti kecuali pencahayaan yang semakin gelap.
Tap…tap… Tiba-tiba langkah kaki itu terdengar sangat dekat, ia tergesa-gesa. “Halo, apa ada orang di dalam?” katanya setengah berteriak. Ah, sekuriti wanita, pikirku. Sesaat sebelum aku menjawab bahwa aku di dalam, jantungku benar-benar berhenti saat mendengar kalimat selanjutnya yang ia ucapkan. “Please, semoga yang satu ini kosong…” Kakiku mati rasa. Aku hampir pingsan ketika knop pintu berusaha dibuka dari luar. Kupejamkan mataku rapat-rapat sembari melafalkan doa apapun yang kuhafal. Benar saja, pintu itu segera terbuka.
Ku beranikan diriku untuk membuka mata. Perasaanku bercampur aduk melihat tidak ada siapapun di luar sana. Tanpa menunggu lebih lama, aku segera berlari menjauhi ruangan itu. Samar-samar kudengar suara pintu ditutup di belakang sana. Aku bersumpah itu bukan aku. Pun tidak ingin tahu siapa yang menutup pintu itu. Satu-satunya yang kupikirkan saat ini adalah pulang dengan selamat. Aku terus berlari menyusuri lorong panjang yang mengarahkanku langsung ke gerbang sekolah. Aku tidak peduli ranselku yang masih di kelas, atau sepedaku yang masih berada di tempat parkir. Aku merasa sedang diikuti. Aku takut, sangat takut. Ini adalah pengalaman pertamaku. Lalu apakah yang baru saja terjadi? Bagaimana bisa suaranya mirip suaraku? Dan kalimat-kalimat itu…
Kulanjutkan langkahku yang terasa semakin melambat ini.
Baca Juga: Seorang Pria Putus Asa
BekelSego adalah media yang menyediakan platform untuk menulis, semua karya tulis sepenuhnya tanggung jawab penulis.