
Seseorang terlihat masih betah merebahkan tubuhnya di atas kasur, enggan untuk beranjak. Kasur memang menjadi tempat terbaik dalam hal memberi kenyamanan. Malam ini ia tampak gamang membuka ponselnya. Dia tak tahu lagi harus menuliskan apa, dan memulainya dari mana.
Dia mencoba menuliskan sebuah potret kehidupan yang sama sekali belum pernah dijumpainya. Dia masih saja bingung, apalagi untuk menggambarkan kerinduannya. Matanya menerawang memandangi langit-langit kamarnya. Imajinasinya mulai liar kemana-mana. Tampaknya dia sedang mencoba fokus. Mencari ketenangan di sela-sela gusar yang melanda.
Saat ini, dia harus menuliskan sebuah nama lewat tarian jemarinya yang jelita. Sebuah nama yang beberapa hari terakhir ini selalu mengusik ketenangannya, mengacaukan separuh akal sehatnya.
Tentang bagaimana ciri fisiknya, bagaimana lembut tutur katanya, bagaimana perangainya, dan tak lupa tentang bagaimana perasaannya.
Sebuah perasaan?
Perasaan apa?
Perasaan siapa?
Bahkan tentang perasaannya sendiri pun, dia masih belum juga mengerti. Masih begitu kesulitan memahami. Dia terlalu naif atau memang bodoh? Entahlah! Pernyataan itu sedikit kelewatan. Namun tampaknya dia sama sekali tak keberatan. Justru dengan santainya dia mempersilakan. Silakan caci aku, silakan maki aku, silakan cemooh aku, katanya sembari menyunggingkan senyum yang sulit diartikan.
Waktu menunjukkan dirinya yang semakin larut. Dia menoleh ke arah jam dinding yang tergantung itu. Berniat mengubur dalam-dalam perasaannya pada hakikat yang durjana. Menghardiknya hingga keringat bercucuran.
Namun, sebuah keraguan masih saja bergelayut di dalam dirinya, memenuhi benaknya. Terus berputar-putar di kepalanya seperti kipas angin yang tergantung di langit-langit kamarnya. Tak mau berhenti, bahkan untuk berjeda sekalipun. Benar-benar egois, bukan?
Apakah masih perlu baginya untuk terus menulis sembari menangguhkan hasrat jemarinya mengetikkan kata-kata murahan itu? Atau, haruskah ia berhenti saat ini juga?
Namun semuanya terlanjur sudah. Tulisannya terangkai sudah, sejauh ini. meski tak ada seorang pun yang bisa memahami.
Terlalu abstrak memang. Memang abstrak. Benar-benar abstrak. Sungguh abstrak. Sembari tersenyum kecut, dia terus mencoba menghibur hatinya. Menjadi badut untuk dirinya sendiri. Menertawakan segala tindakannya sendiri. Berusaha mencari letak kebahagian miliknya yang tampaknya selama ini masih bersembunyi.
“Huufftt…” Dia mengembuskan napasnya, gusar.
Abstrak?
Tahu apa dia tentang kata itu? Apakah perasaan yang tengah dirasakannya serumit itu? Tidak berwujud, tidak berbentuk. Bahkan nyaris remuk.
Dan dia masih saja memandangi tulisannya itu dengan sayu. Dia merasa tulisannya sedikit nyeleneh, aneh. Sama sekali tak menggambarkan sosoknya selama ini. jangan-jangan dia sudah kerasukan wujud makhluk yang aneh?
Apa yang sebenarnya telah ia tuliskan?
Adakah yang bersedia membaca tulisannya nanti?
Untuk siapa sebenarnya tulisan itu?
Tulisannya masih terlalu buruk, benar-benar buruk. Tampaknya bukan hal yang mudah untuk mendeskripsikan gambaran siluet dalam tulisannya itu. Namun bukankah dia sudah mencoba sebisa mungkin, berusaha sebaik mungkin? Mengapa masih saja meremehkannya?
Sekarang, dia tidak akan melewatkan setiap keadaan hanya dengan memapah pada sebuah bayang-bayang kenangan. Dia ingin menyimpannya dalam suatu bentuk yang lain. Menyimpan ilusi atas seseorang yang merusuhi akal sehatnya akhir-akhir ini.
Dan hanya inilah yang dia butuhkan, sebuah aplikasi buku catatan dalam ponsel dan ketenangan malam yang panjang. Dia terlalu sensitif. Sisi melankolisnya mulai merajai hati lebih parah sejak dia diam-diam mengagumi sosok seseorang itu. Namun hal itu tak mengubah apa pun. Dia tetaplah dirinya yang naif dan nyaris bodoh.
“Aku ingin menjadi pagimu, sekalipun tak menyenangkan. Menjadi yang pertama kali kau tatap, usai terlelap. Menyajikan sebuah pelukan hangat, saat kau terlalu sibuk memikirkan bagaimana wujud senja yang memikat.”
Baca Juga: Getaran Hati dalam Pena
Ah, bukankah terlalu berlebihan? Sungguh, itu sedikit keterlaluan.
Akhirnya dia sadar juga. Bagaimana bisa kalimat-kalimat murahan itu terangkai begitu saja? Dibacanya berulang-ulang apa yang sudah ditulisnya itu. Dan dia nyaris tak percaya dengan ini semua.
Dia menatap gusar layar ponselnya. Perasannya berkecamuk. Matanya sudah semakin mengantuk.
Simpan?
Hapus?
***
“Simpan kisah ini baik-baik!” katanya.
Pada suatu malam, saat hujan mengguyur terlampau deras, seorang gadis tengah termenung di balik jendela kamar sembari menatap nanar pelataran yang kebasahan. Matanya yang tampak sayu itu, tak kalah deras ketika rinai lain juga berderai dari kedua sudutnya.
Sakit.
Padahal ia tak dirutuki oleh rinainya. Ia tak kebasahan dan sama sekali tak menggigil kedinginan. Hanya saja untuk saat ini, dadanya benar-benar terasa sesak.
Gelegar petir yang menyambar, semakin menambah deritanya. Meraung-raung di kedua telinganya, menerobos masuk dan menyayat relung jiwanya.
Mengapa ia harus merasa sesakit ini tiap kali menyaksikan hujan?
Mungkinkah karena menjadi hujan itu menyakitkan? Ia harus dijatuhkan jutaan kali, meski ia memaksa terbang setinggi mungkin.
Perlahan, tangan mungil gadis itu menyeka bulir yang mengalir di kedua pipinya. Ia mencoba tersenyum, namun terlihat sekali bahwa itu dipaksakan. Ia sama sekali tak berkutik. Seperti terhipnotis, ia dipaksa untuk tetap beradu tatap dengan hujan.
Hujan, hujan, dan hujan.
Hujan jatuh, tangisnya luruh.
Air hujan menguap, ingatannya pun lenyap.
Apa yang sebenarnya sudah ia lupakan tentang hujan? Mengapa rasa sakit itu terus menjadi misteri dari benaknya?
“Hujan mengutukmu!” kata seseorang.
Karena kamu telah berani menghapus memori tentangnya. Ya, tentang hujan itu. Yang telah dilupakan gadis malang itu.
Baca Juga: Pamit
***
“Hapus saja ingatan yang tak lagi berguna itu!”
Seorang penulis tampak sedang berkutat dengan pena dan tumpukan kertas di atas meja. Digerak-gerakkannya pena itu pada kertas sehingga penuh dengan rangkaian kata, kalimat, dan paragraf.
Malam hampir tiba pada puncaknya dan bunyi gerimis yang berdentum-dentum di atap rumahnya, telah menyatu dengan imajinasi penulis itu.
Sudah berlembar-lembar halaman kertas itu penuh dengan tulisan mahakaryanya. Memang benar, semua tulisannya disukai banyak orang dan dimuat di berbagai media cetak maupun internet. Dia memang seorang penulis terkenal.
Penulis itu memang ahlinya dalam memainkan imajinasi dan menuangkannya dalam bentuk tulisan. Ada banyak jenis karya yang telah dihasilkan. Novel, cerpen, puisi, dan berbagai jenis tulisan yang lain. Semuanya sangat luar biasa. Tak salah jika dia menjadi seorang penulis terkenal.
Pena penulis itu sudah banyak menorehkan tintanya. Dan kini tibalah ia pada halaman terakhir karya yang dibuat penulis itu. Ya, sebuah cerpen hampir selesai dibuat penulis itu hanya dalam kurun waktu kurang dari satu jam.
Beberapa waktu lalu, dia juga sudah menghasilkan beberapa puisi. Kemarin ia menyelesaikan sebuah novel. Dan hari-hari kemarin lainnya juga demikian. Penulis itu selalu mampu menyelesaikan tulisannya dengan cepat. Dia benar-benar penulis hebat, bukan?
Kurang satu paragraf lagi, batin penulis itu. Dia akan mencapai akhir cerita yang dibuatnya. Pena itu masih terus bergerak ke kanan. Dan setelah sampai pada ujung, ia turun ke bawah, lalu bergerak ke kanan lagi, hingga sebuah tanda titik mengakhiri langkahnya.
“Akhirnya aku berhasil menyelesaikan satu cerpen lagi.” ujar si penulis.
Penulis itu merasa senang. Ia tampak bangga pada dirinya sendiri. Dipandanginya hasil tulisannya itu. Ia sangat puas. Namun tiba-tiba terdengar sebuah suara.
“Kau bangga padaku?”
Penulis itu terkejut. Pasalnya tidak ada seorang pun yang bersamanya saat ini. Ia seorang diri di kamarnya. Benar-benar sendiri. Lalu siapa yang sedang berbicara?
“Kau bangga padaku atau pada kemampuanmu yang akhirnya bisa menghasilkan aku dan kawananku?”
Suara itu muncul lagi. Penulis itu masih celingukan mencari sumber suara. Bola matanya bergerak ke atas, bawah, kanan, dan kiri. Kepalanya ia putar memandangi seisi ruangan kamar. Namun tak ada siapa-siapa.
“Aku ada di sini, di depanmu.”
Si penulis tersentak. Suara itu ada di depannya. Apakah suara itu berasal dari setumpuk kertas berisi mahakarya yang baru saja ditulisnya? Bagaimana bisa tumpukan kertas itu bersuara? Apakah penulis itu hanya berhalusinasi?
Ia mencoba menajamkan indera pendengarannya lagi. Perlahan, didekatkannya telinga sebelah kiri ke arah tumpukan kertas itu. Saat kepala penulis itu hampir menyentuh bagian atas meja, ia hanya bisa terdiam. Tak ada suara-suara yang muncul. Hening. Malam berhasil menjalankan tugasnya kembali.
“Kau kah itu yang berbicara?” tanya penulis itu.
“Ya, ini aku.”
***
“Inilah cerita abstrak yang sesungguhnya.”
Sial, aku harus menyimpannya atau menghapusnya?
Baca Juga: Tukimin Sakit Hati




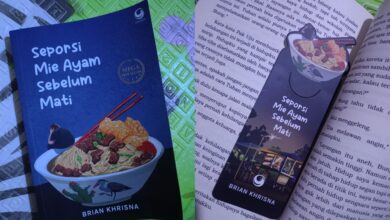













I’m sorry, what can I do for you?