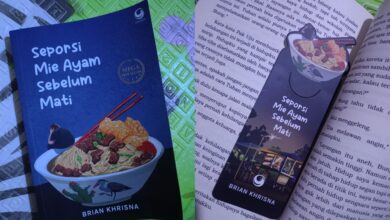“Jo”, demikianlah orang sekitar mengenalnya. Lelaki berbadan kekar, rambut kribo, dan sebuah codet di pipi – bekas goresan pisau dalam perkelahian, membuat ia ditakuti di kampungnya. Sebagai pemuda perkasa dan nakal, ia menjadi terkenal dan sohor. Bahkan kesohorannya itu sampai ke telinga Kiai Zubair, seorang ternama, pengasuh pesantren di kampung seberang.
***
“Jo? Siapa nama lengkapnya? Sepertinya saya pernah dengar nama itu.” Kiai Zubair bertanya pada santri yang memberitakan perihal itu padanya.
“Tidak tahu, Pak Kiai. Saya juga dapat berita ini dari peristiwa kemarin. Pemuda itu melarang kami berdakwah dan mengancam kami.” Sambil menunduk, santri itu menceritakan duduk perkaranya pada Kiai Zubair.
Kiai Zubair manggut-manggut. Janggut putih di dagunya diplintir sambil menghela napas panjang, Kiai Zubair mempersilahkan santri itu beristirahat.
“Besok temui Jo. Ajak dia bicara baik-baik,” tiba-tiba Kiai Zubair berbicara, entah pada siapa. Salah satu santri yang sedari tadi di sampingnya heran dengan yang dilakukan kiainya itu.
“Pak Kiai menyuruh saya?”
“Tidak Amrun. Bukan kamu. Saya tadi sedang menyuruh salah satu santri di pesantren ini. Kamu, belajarlah dulu ilmu syariat, tak perlu heran dengan apa yang saya lakukan,” dengan sabar Kiai Zubair menjawab pertanyaan santri itu.
“Santri di pesantren ini juga, Pak Kiai?” Santri itu semakin heran. Toh, di ruangan itu hanya ada mereka berdua. Namun, tanpa pikir panjang, ia segera pamit ke kamarnya untuk segera menyiapkan hafalan-hafalan esok hari.
***
Keesokan malamnya, di sebuah rumah kosong, Jo merapalkan ajian pesugihan. Dengan bekal nekat, komat-kamit mulut Jo membuat sunyi di rumah itu mendadak merdu.
“Anak muda, apa yang kau lakukan di rumah ini?” Tiba-tiba ada suara mengejutkannya. Suara yang menggelegar, meledak-ledak. Suara itu menghentikan ajian-ajian Jo.
“Aku ingin kaya. Tolong aku,” suara yang keluar dari mulut Jo seperti membisikkan sebuah iba. Tapi, tak ada jawaban yang segera. Tak ada yang instant.
“Siapa kamu? Di mana wujudmu? Tunjukkan padaku batang hidungmu.” Jo berteriak, sekencang mungkin, berharap suara tanpa wujud itu membalas pertanyaannya.
Malam semakin larut. Jo tak mendapat jawab. Sedikit pun.
“Kurang ajar. Siapa kau? Ayo keluarlah. Atau kalau kau memang tak mau keluar. Tunjukkan padaku, bagaimana cara menjadi kaya. Aku ingin cepat kaya.”
Detik demi detik berlalu. Azan subuh sudah berkumandang. Jo masih tetap tak ada jawab. Ia berpikir untuk kembali ke rumahnya. Tapi, Ia kemudian duduk cemas. Ia baru ingat bahwa ia tak punya rumah. Rumahnya dijual untuk membeli narkoba. “Aku harus pulang ke mana?” Pikirnya dalam hati. Lagi pula, Jo terlanjur tak disukai orang-orang di kampungnya.
Tiba-tiba gelegar suara itu datang lagi, “Anak muda, pergilah ke kampung seberang. Di sana, engkau akan bertemu dengan Kiai Zubair.”
Suara itu akhirnya memberi petunjuk padanya.
Seakan-akan ada yang bentak keluar dari ceruk hatinya paling dalam. Ia ingat, Kiai Zubair pernah ditolongnya menyeberangi sungai. Kala itu, arus begitu deras. Hanya ia yang berani melewatinya dengan rakit dari bilah bambu yang diikat rapat-rapat. Sampai akhirnya Kiai Zubair mengangkatnya sebagai murid di pesantren At-Taubah di kampung seberang. Waktu itu sekitar umur 17 tahun. Tapi, karena penyakit bapaknya ia harus pulang ke rumahnya dan merawat bapaknya yang terkena penyakit Alzheimer hingga wafat.
Ibunya pergi meninggalkan mereka berdua setelah bapaknya tak lagi bisa bekerja. Hingga seperginya dari Pesantren dan kematian bapaknya, ia terjerumus ke jalan yang salah. Ia menjadi seorang pemakai narkoba. Lama kemudian, karena keuangan yang menipis, ia mengedar narkoba demi melangsungkan kehidupan.
“Ya, aku harus temui Kiai Zubair. Tapi aku malu. Aku takut beliau tak mau menerimaku lagi menjadi murid.” Air matanya menetes satu-satu. Kemudian membanjiri pipinya. Kemudian membasuh hatinya yang kotor.
Selang beberapa saat, setelah Jo menghapus air matanya, gelegar suara itu muncul lagi, “Anak muda. Tidak ada kata malu untuk belajar kembali. Dan perihal takut, bukankah takut hanya kepada Allah?”
Ya, gelegar suara itu menambah kebesaran hati Jo untuk kembali. Ia melangkahkan kakinya ke selatan, ke arah sebuah masjid. Sambil berjalan tunduk sepanjang lorong, hujan turun rintik-rintik seperti air matanya yang terus mengalir, walau sudah dihapus berkali ulang.
Subuh yang ringkih. Jo meringkik, memohon ampunan pada Allah.
Tiba-tiba dari belakang, seusai doa dipanjatkannya, seorang lelaki memegang pundaknya. “Zubair? Masih ingat saya? Saya Ibrahim, teman sekamarmu di pesantren.”
Jo memalingkan wajahnya. Ibrahim? Ia mencoba mengingat-ingat wajah yang berada tepat di hadapannya. “Ibrahim? Ibrahim Bin Abdullah? Kau? MasyaAllah,” Jo yang murung tiba-tiba girang menyaksikan wajah yang ia kenal akrab beberapa tahun lalu. Mereka berpelukan. Sangat erat.
“Kau kerja di mana sekarang?”
“Aku mengabdi pada pesantren, ya, mengajar. Kau sendiri?”
“Aku tak tahu mau ke mana lagi. Aku tak punya apa-apa, aku merasa hidup sendiri.”
“Ah, jangan gitulah, kan masih ada Allah, ada aku, ada Kiai. Kalau kau mau, kau boleh tinggal di pesantren. Kiai pasti senang.”
Setelah fajar bangkit dan matahari menumbuhkan dirinya hingga bumi kembali cerah seperti hari-hari biasa, mereka pun pergi menghadap Kiai Zubair. Dengan senang hati, Kiai Zubair menjabat tangan Jo, lalu ia memeluknya dan mencium kening santri kesayangannya itu.
“Selamat datang kembali, Zubair. Kita bisa mulai dari mana?” Kiai Zubair menanyai Jo, sampai mana kedalaman ilmunya.
Jo hanya terdiam dan berlutut sambil menangis di hadapan Kiai Zubair.
“Tak apa, saya paham. Baiklah, kita hatamkan dulu Syariat. Lantas setelah itu, kamu boleh belajar, Thariqat, Hakikat, dan Makrifat.”
***
Setelah kematian Kiai Zubair. Hingga tua, Jo menetap di pesantren dan menjadi pengasuh bersama-sama dengan Ibrahim bin Abdullah. Sampai suatu ketika, ia mendapati dirinya di dalam cermin. Apakah Allah selalu mempunyai jalan yang indah bagi hamba-hambanya? Ia selalu bertanya-tanya.
***
“Jo? Saya ingat nama itu. Ya, ia nama panggilanku dulu. Ada apa?”
“Begini pak Kiai, orang itu selalu menghalangi kami berdakwah. Kami jadi risih. Tapi, kami tak mungkin mengambil sikap kasar. Bukannya batu tidak boleh dibalas dengan batu, pak Kiai?”
“Kau tahu, siapa orang itu?”
“Tidak.”
“Orang itu adalah santri di sini beberapa tahun silam. Tapi, ia harus pulang lantaran penyakit ibunya kambuh. Sampai sekarang ia belum pernah kembali ke sini. Tenangkanlah dirimu. Jaga santri-santri yang lain.”
“Baik pak kiai.”
Jo lalu seperti berbicara sendiri, “Panggillah anak itu ke sini.”
***
Sore yang samar-samar. Jo melihat-lihat pemandangan di sekitar masjid. Dari jauh, ia melihat seseorang berjalan menuju arahnya. Mendekat. Lalu akhirnya sampai.
“Gelegar suara itu sudah menyampaikan pesan itu, Zubair?” Jo bertanya dengan sabar pada lelaki yang baru melepas lelah dengan memeluknya sangat erat itu.
“Sudah Kiai.”
“Baiklah, kita bisa mulai dari mana?”
“Terserah Pak Kiai Zubair saja. Saya manut jenengan.”
Lalu, dari mata keduanya, tetes-tetes air mata bercucuran. Membasahi pipi mereka. Membasuh hati mereka.
Baca Juga: Instagram