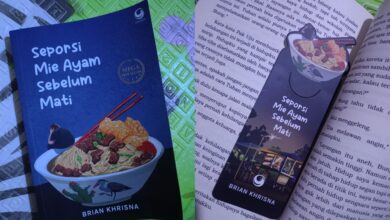Dua puluh tahun Ia menyaksikan wajah muram di kafe itu. Tapi ada beberapa hal yang tak dimengertinya. Tentang dahi-dahi manusia yang bergaris-garis dan memberi nama sebuah sifat kemanusiaan. Atau bahkan satu dahi bisa diberi beberapa nama sifat.
Sebuah buku puisi atau beberapa buku disungginya setiap kali penyair menamu. Tapi, para penyair selalu berdiskusi pula pada dahinya. Penyair-penyair membuat dirinya terkantuk-kantuk bahkan sunyi. Sunyi sekali. Tak ada yang bisa dikatakan pada penyair itu. Hanya sepi, dan kaki yang kaku menyangga laptop, kertas, pulpen, dan sebuah buku harian. Berumpun-rumpun kerisauan di dahi penyair yang menghampiri berusaha dihitungnya.
Aku sebagai temannya dan juga teman penyair merasa sedih tak mampu menyaksikan dahi mereka. Tapi, setiap kali penyair-penyair itu pergi, Ia selalu menceritakan padaku perihal dahi yang mengkerut setiap waktu datang menghampiri dan menjadi congkak bahkan tak mau memperdulikanku.
“Sudah terlalu lama kau menjadi bagian hidup dari mereka, tapi, kau tak melihat segalanya, bukan?” ucapnya, setelah dua puluh tahun lebih satu detik aku dan dia di tempatkan di sudut kafe Oriez, yang digemari para penyair lantaran rasa kopi, yang berbeda, Kopi rasa madu. Entah bagaimana pikiran si Tua itu. Mungkin Si Tua itu sudah bosan dengan kehidupan yang pahit. Lantas, apakah dunia ini diciptakan hanya untuk “pahit” belaka? Si Tua itu selalu bertanya pada diri sendiri dan membeberkan pada istri madunya sesekali.
Tidak lama setelah detik pertama sehabis dua puluh tahun itu, seorang lelaki datang menamu. Pukul 00.07. Orang-orang sudah berpulang dan mengerami anak-anaknya, maklum, aku terlalu sering mendengar kata ayam dari mereka. Jadi tak ada salah jika aku mengatakan demikian, bukan? Ya, lelaki itu datang dengan dahi cerah. “Ada cahaya di dahinya.” Ia membisikiku pelan-pelan.
“Aneh, untuk apa dia datang kemari? Aku tak pernah melihatnya”
Aku tak paham apa maksudnya. Aku hanya mendengar. Sebagai pendengar yang baik, selalu saja aku mengiyakan apa-apa yang dilontarkannya. Toh, di sudut ini, kami hanya berdua dan tak mungkin ada yang menghiraukan kami. Setidaknya aku punya pasangan. Tidak seperti Adam yang diciptakan tanpa pasangan dan luntang-lantung tak karuan lalu tertidur dalam sepi sebelum Eva diciptakan. Ah, mengapa aku selalu membahas manusia? Tapi bahasan yang paling pelik kan manusia. Komplit dan berumpun-rumpun.
Tapi, perihal cinta, aku tak kan mau disamakan dengan manusia. Toh, penampakan dahi mereka selalu berubah-ubah. Bahkan ada yang sering datang dengan dahi kerut. Tapi, lelaki ini sangatlah berbeda, bercahaya? Apakah dia seorang yang sengaja diturunkan tuhan? Atau dia memiliki kesaktian dan amalan-amalan jahanam? Aku tidak tahu.
“Lelaki itu bermata satu.” Ia berbisik lagi, takut-takut jika ada yang memerhatikan kami. Tapi, kami tak bisa berdekatan. Tiba-tiba, lelaki itu menggeserku. Aku semakin dekat dengannya, “Bagaimana?” Aku bertanya sungguh-sungguh. Baru kali ini kudengar lelaki punya dahi bercahaya dan bermata satu.
“Sebentar.” Ia mengeja sesuatu.
Aku menatapnya heran.
“Sketsa.” Ia berteriak sangat keras hingga membuatku merasa kesal. Tak pernah ia berlaku sedemikian bodohnya. Teriak tak akan mengubah nasib.
“Bukankah kita sudah berjanji tak ada teriakan, sudah banyak jerit dari jiwa manusia yang menderita. Kita tak perlu ikut-ikut, mau kau kusebut epigon?” Aku kecewa. Ia melanggar perjanjian yang telah kami sepakati dengan sumpah serapah tujuh hari setelah pertemuan pertama, di mana saat itu kami berdua memutuskan untuk berhenti meminta pertolongan dan mengobati diri dalam sunyi.
“Tidak, jangan khawatir, toh tak ada yang mendengar kita.”
Ya, baru kuingat, perjanjian selalu punya alasan untuk diingkari. Ia lalu tertawa.
“Ternyata lelaki itu orang gila. Si tua sebentar lagi mengusirnya. Lihat saja nanti.”
Aku percaya saja dengan kata-katanya. Namun, kekecawaan yang mengahampiriku tak bisa pergi. Tak ada alasan untuk membuatku terima ingkarnya perjanjian. Kalau penyair bisa menuliskan kekecewaan dan kesedihan menjadi berbait-bait sajak dan dikirim ke koran lalu mendapatkan honor. Tapi, aku tak mungkin melakukan itu. Selama hidup, aku hanya bisa mendengar kata-kata dan janji-janji darinya. Ia lebih banyak mengerti tentang kehidupan dan manusia dibanding aku. Melihat wajah saja, aku tak bisa, apalagi melihat dahi yang mengkerut ketika penyair menulis. Aku ingat benar, siapa yang memulai perjanjian itu: Ia. Ia yang memulai dan Ia yang mengingkari. Sungguh, tak ada beda dengan manusia. Aku juga tak paham mengapa ia berlaku begitu.
Setelah hari ketujuh tak ada jawab dariku kalau ia bercerita. Seorang lelaki datang tepat pukul 12.12. Ia berteriak lagi. Kemerahanku semakin menjadi-jadi. Ah, apakah mungkin aku akan memaafkannya? Kesalahan pertama saja belum kumaafkan sepenuhnya, malah ia berulah lagi. Aku benar-benar bingung. Mengapa ia berteriak dengan kuat lalu berhenti dan diam seribu bahasa? Tidak-tidak, pasti ada yang disembunyikan. Tapi, apa? Apa yang membuatnya begitu? Aku penasaran.
Aku selidiki sikapnya. Tak ada hasil. Ah, jika aku malu bertanya, aku tak mungkin dapat informasi. Tapi, apakah harus, aku percaya padanya? Bukankah ia telah mengingkariku dua kali? Hal yang sama pula.
Kupikirkan ulang sekali, dua kali, dan akhirnya luluh juga hatiku untuk bertanya.
“Lelaki itu berjubah putih, kopiah putih, sorban putih, dan jenggot putih. Aku takut sekali.” Dengan nanar tatap matanya, ia bercerita padaku.
Sikap congkak aku haturkan padanya. Bagaimana mungkin ia takut pada lelaki itu, padahal ia pernah bercerita hal serupa dua tahun lalu.
“Ia sekarang beringas. Tidak seperti dulu. Mukanya seram.”
Ah, Ia mulai ingat rupanya, kalau lelaki itu lelaki yang sama. Toh dasar ia memang tak dapat dipercaya sepenuhnya.
“Tidak-tidak. Jangan berprasangka buruk. Dua tahun lalu lelaki itu datang kemari dengan senyum manis dan mencatat surat-surat pada instansi. Aku lihat beberapa lembar kertas berkop hijau.” Ia bercerita runtut. Tak ada satu pun aku pahami. Tapi, melihat gayanya bercerita, kali ini ia benar-benar serius dan terlihat cemas.
“Aku dengar sendiri, beberapa hari yang lalu, ada seorang penyair datang kemari dan menghujatnya habis-habisan lewat tulisan. Oh, iya, penyair itu, tidak setuju dengan beberapa sikap lelaki ini.” Ia melanjutkan kisahnya dan sesekali mengingat-ngingat sesuatu. Barangkali masih ada yang terlupa.
Ia perhatikan lelaki yang baru datang tadi, dan dengan hati-hati ia berbisik padaku, “Lelaki itu terlihat takut. Dahinya banyak kerutan. Kemarin-kemarin, ia sangat bersemangat. Mungkin benar kata orang beberapa hari yang lalu itu kalau ia lelaki ini jadi tersangka makar dan mau membuat negara baru. Bukankah ini bahaya?” ia berlagak pintar dan berusaha memengaruhiku seperti seorang provokator.
“Lalu, imbas bagi kita, apa?” Aku tak pernah dan tak mau peduli terkait hal itu. Toh, aku tak tahu pula, imbasnya buatku.
“Kau memang selalu apatis, setidaknya kita harus memikirkan negara, bukan?”
“Negara? Negara macam apa yang harus kita pikirkan? Kita tak usah muluk-muluk. Sudah ada yang memikirkan.”
“Tapi, kau, tahu tidak? Banyak orang yang mengaku-ngaku memikirkan negara. Tapi, apa. Hasilnya tak ada. Nol besar. Banyak sekali orang yang mengaku akan mewakili rakyat dan akan membantu untuk mensejahterakan maasyarakat. Semua itu, hanya wacana. Tak ada yang bisa dipercaya. Janjinya begini, hasilnya begitu.” Ia berbicara panjang lebar. Nampaknya, ia lupa kalau perkaataannya telah menampakkan sifatnya. Dasar hipokrit, batinku berontak, tapi urung aku ucapkan padanya.
“Kring..kring” Si Tua mengangkat Telepon.
“Iya, benar Pak.. Tapi Jangan sekarang pak.”
Tak lama setelah itu, dua orang berbadan tegap datang dengan tergesa. Si Tua diringkus. Ia berteiak “Jangan, jangan. Saya tidak terlibat aksi itu.” Dua lelaki berbadan tegap itu tak memperdulikannya. “Kami hanya melaksanakan tugas. Silahkan dijelaskan di kantor.”
Lalu dengan tatapan yang tajam, ia berkata padaku, “suatu hari nanti, kita akan berpisah. Kalau bukan kehidupan yang memisahkan kita, seperti Si Tua dan istri madunya, maka kematian yang kan memisahkan kita.”
Aku hanya diam, hatiku berkata lain, “bukankah kematian telah menimpa kita sejak pohon-pohon habis dibakar manusia-manusia yang tak bertanggungjawab?”
Kafe tutup, tak ada lagi dahi, penyair yang sering datang itu telah diringkus polisi dan dipenjara 4 bulan, lelaki bersorban itu kabur ke luar negeri, dan kami menunggu pemilik baru.
***
Baca Juga: Perseteruan Dengan Waktu